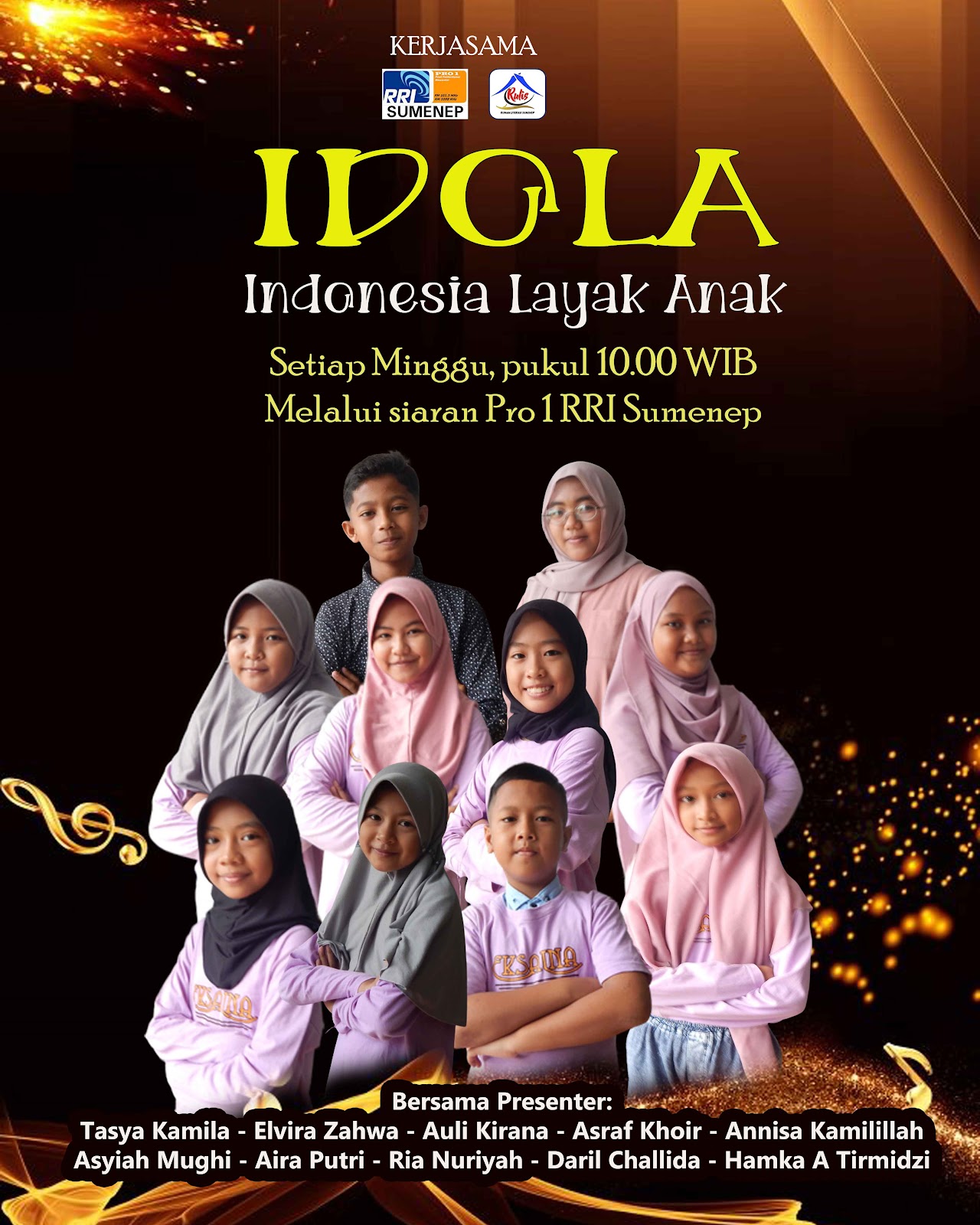Momentum Sumpah Pemuda: Dari Sejarah ke Tantangan Pemuda Hari Ini
Api yang Tak Boleh Padam
Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati salah satu tonggak sejarah paling penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan: Hari Sumpah Pemuda. Sebuah momen monumental di mana semangat persatuan melampaui batas-batas kedaerahan, suku, dan bahasa, untuk menegaskan satu identitas: Indonesia.
Namun, delapan dekade lebih setelah ikrar itu diucapkan, pertanyaan besar pun muncul: bagaimana kondisi pemuda Indonesia hari ini? Apakah semangat Sumpah Pemuda masih hidup di tengah derasnya arus globalisasi, disrupsi digital, dan kompleksitas persoalan sosial?
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menengok kembali ke belakang — ke tahun 1928, ketika semuanya bermula.
Sejarah Singkat Sumpah Pemuda: Dari Percikan ke Api Pergerakan
Awal abad ke-20 adalah masa yang pelik bagi rakyat Nusantara. Penjajahan Belanda menindas dalam berbagai bentuk: ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Namun di balik keterjajahan itu, muncul generasi muda yang haus ilmu dan ingin merdeka — bukan sekadar bebas secara fisik, tapi juga bebas berpikir.
Perkumpulan-perkumpulan pelajar seperti Budi Utomo (1908), Jong Java, Jong Sumatra Bond, Jong Ambon, dan organisasi lain tumbuh di berbagai daerah. Mereka awalnya berjuang untuk kepentingan kedaerahan, memperjuangkan identitas asal masing-masing. Namun seiring waktu, muncul kesadaran baru: bahwa penjajahan tidak mengenal suku atau asal, dan kebebasan hanya dapat dicapai dengan bersatu sebagai satu bangsa.
Kesadaran itu mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda II, yang diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928 di Batavia (sekarang Jakarta). Di sana, para wakil organisasi kepemudaan berkumpul, berdiskusi, dan menyatukan pandangan. Tokoh-tokoh seperti Soegondo Djojopoespito, Wage Rudolf Supratman, Muhammad Yamin, dan Sarmidi Mangunsarkoro menjadi bagian penting dalam peristiwa bersejarah itu.
Pada hari terakhir kongres, lahirlah Sumpah Pemuda, sebuah ikrar yang sederhana namun sangat mendalam:
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Tiga kalimat ini menjadi dasar kokoh berdirinya bangsa Indonesia modern. Ia bukan hanya deklarasi simbolik, tetapi manifestasi dari kesadaran kolektif bahwa perbedaan adalah kekuatan, dan persatuan adalah jalan menuju kemerdekaan.
Makna Sumpah Pemuda: Persatuan, Identitas, dan Kesadaran Kebangsaan
Sumpah Pemuda bukan sekadar teks historis yang dibacakan setiap tahun di sekolah atau upacara. Ia adalah sebuah manifesto pemuda tentang tiga hal mendasar: persatuan, identitas, dan kesadaran kebangsaan.
1. Persatuan di Tengah Keberagaman
Indonesia sejak dahulu kala adalah mosaik kebudayaan. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan ratusan bahasa daerah membentuk keanekaragaman yang luar biasa. Dalam konteks itu, Sumpah Pemuda hadir sebagai “lem perekat” yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan nasional. Pemuda-pemuda 1928 menyadari bahwa tanpa persatuan, perjuangan melawan penjajahan hanyalah mimpi kosong.
2. Identitas sebagai Bangsa Indonesia
Sebelum Sumpah Pemuda, identitas “Indonesia” belum menjadi kesadaran umum. Masyarakat lebih mengenal diri mereka sebagai orang Jawa, Minang, Bugis, Ambon, atau Bali. Sumpah Pemuda menandai lahirnya “kesadaran kebangsaan” — sebuah titik balik dari rasa kedaerahan menuju rasa kebangsaan yang menyeluruh.
3. Bahasa sebagai Alat Persatuan
Bahasa Indonesia, yang diambil dari bahasa Melayu, menjadi simbol sekaligus alat untuk menyatukan bangsa. Pemilihan ini bukan kebetulan, melainkan keputusan cerdas: bahasa yang sederhana, terbuka, dan sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah perdagangan Nusantara.
Dalam konteks modern, semangat ini mengajarkan kita bahwa komunikasi adalah fondasi utama dari persatuan sosial.
Pemuda dan Perannya Setelah Kemerdekaan
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, peran pemuda tidak berhenti. Justru, mereka menjadi motor perubahan di setiap fase sejarah bangsa.
Pemuda ada di barisan terdepan dalam berbagai peristiwa besar: peristiwa 1945, 1966, 1998, hingga gerakan sosial dan lingkungan di masa kini.
- Tahun 1945: Pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
- Tahun 1966: Mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan politik dan mengakhiri era Orde Lama.
- Tahun 1998: Gelombang reformasi yang menggulingkan rezim Orde Baru juga digerakkan oleh mahasiswa yang menuntut demokrasi dan keadilan.
Dari masa ke masa, satu hal tak berubah: pemuda selalu menjadi agent of change — pembawa ide-ide baru, penantang status quo, dan harapan bagi masa depan bangsa.
Tantangan Pemuda di Era Modern
Namun zaman telah berubah. Jika dulu musuh utama adalah penjajahan fisik, kini bentuk “penjajahan” jauh lebih halus — ekonomi, budaya, dan teknologi.
Pemuda kini berhadapan dengan tantangan yang kompleks, mulai dari kemiskinan struktural, pengangguran, krisis identitas, hingga distraksi digital.
- Krisis Identitas di Era Globalisasi
Budaya global membentuk gaya hidup instan dan serba viral. Nasionalisme kerap dipersempit menjadi slogan, bukan lagi semangat yang hidup. - Tantangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Menurut BPS (2024), tingkat pengangguran terbuka masih didominasi oleh kelompok muda, bahkan di kalangan terdidik. - Kesenjangan Digital dan Literasi Teknologi
Di perkotaan, anak muda akrab dengan startup dan AI; di pelosok, banyak yang masih berjuang dengan akses internet.
Ketimpangan ini menciptakan jurang baru dalam kesempatan berdaya. - Krisis Kepercayaan terhadap Politik dan Institusi
Banyak anak muda apatis terhadap politik karena merasa suaranya tak berpengaruh, padahal perubahan struktural hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif.
Peluang dan Harapan: Menuju Generasi Emas 2045
Meski tantangan besar, peluang pemuda Indonesia juga luar biasa. Dengan jumlah lebih dari 70 juta jiwa, Indonesia memiliki bonus demografi yang bisa menjadi kekuatan dahsyat jika dikelola baik.
- Pemuda dan Inovasi Teknologi
Startup seperti Gojek, Tokopedia, dan Ruangguru membuktikan semangat kreatif dan inovatif anak muda Indonesia. - Kesadaran Sosial dan Lingkungan
Gerakan seperti Bye Bye Plastic Bags menunjukkan kepedulian baru terhadap isu lingkungan dan kemanusiaan. - Kolaborasi dan Solidaritas Digital
Media sosial menciptakan ruang solidaritas baru, tempat pemuda dapat berkolaborasi tanpa batas geografi. - Kembali ke Spirit 1928
Semangat Sumpah Pemuda tetap relevan: menjadi bagian dari dunia tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Dari Refleksi ke Aksi
Untuk menjaga api Sumpah Pemuda tetap menyala, dibutuhkan langkah nyata dari semua pihak:
- Pendidikan Karakter dan Literasi Kritis
Pemuda harus dibekali pengetahuan sejarah, etika, dan kemampuan berpikir kritis agar tak kehilangan arah di era informasi. - Ruang Kreatif dan Inklusif bagi Pemuda
Pemerintah dan swasta perlu memperluas ruang inovasi, inkubator bisnis, dan komunitas sosial di seluruh daerah. - Menumbuhkan Kepemimpinan Moral
Kepemimpinan masa depan harus berakar pada integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. - Menghidupkan Kembali Gotong Royong
Nilai kolektif khas Indonesia ini perlu diadaptasi dalam konteks modern: kolaborasi digital, sosial, dan lintas sektor.
Menyulut Api yang Sama di Zaman yang Berbeda
Sumpah Pemuda 1928 adalah kisah tentang keberanian — keberanian untuk bersatu di tengah perbedaan, untuk bermimpi di tengah keterjajahan, dan untuk percaya bahwa bangsa ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain.
Kini, hampir satu abad kemudian, api itu masih harus dijaga.
Bukan dengan menghafalnya, tetapi dengan menghidupkannya: melalui kerja, kreativitas, solidaritas, dan kepedulian.
Pemuda hari ini mungkin tidak lagi berperang melawan penjajah bersenjata, tapi mereka tetap berperang — melawan kebodohan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian.
Dan selama api semangat itu menyala, Sumpah Pemuda akan selalu menjadi napas yang menghidupkan bangsa Indonesia.
*****
( Rulis, dirangkum dari beberapa sumber)Pilihan