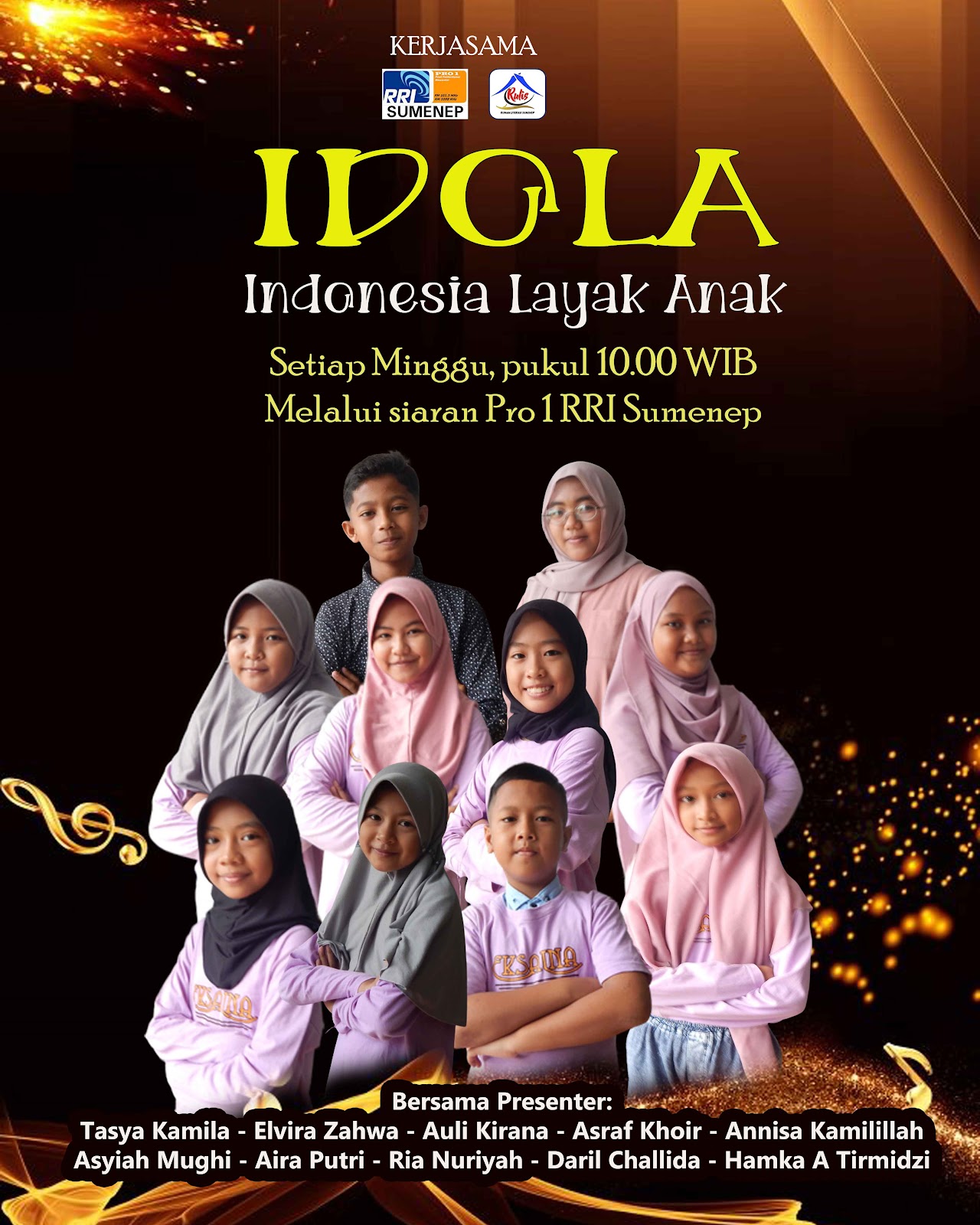Pariwisata, Biang Keladi Runtuhnya Kesenian Lokal?
(Catatan Lepas tentang Budaya, Wisata, dan Ironi yang Tak Pernah Usai)
Ada satu pertanyaan yang selalu menggelitik setiap kali saya menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian daerah yang dikemas untuk wisata: apakah seni ini masih hidup sebagai bagian dari budaya, atau sekadar dipajang sebagai etalase turisme?
Pertanyaan sederhana ini ternyata menyimpan keresahan panjang. Karena di balik gemerlap panggung, kostum warna-warni, dan tepuk tangan para pengunjung yang mungkin datang hanya sekadar “mampir”, tersimpan kenyataan getir: bahwa kesenian lokal kerap kali hanya dijadikan alat promosi pariwisata, bukan lagi ruang ekspresi bagi para senimannya.
Antara Panggung, Promosi, dan Paradoks
Kita tidak bisa memungkiri bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang menjanjikan bagi daerah—terutama di wilayah yang punya potensi budaya kuat seperti Kabupaten Sumenep. Tapi persoalannya bukan pada wisata itu sendiri, melainkan pada bagaimana konsepnya dijalankan.
Alih-alih memberi ruang bagi seniman untuk tumbuh dan berkreasi, pariwisata justru menjadikan kesenian sekadar bumbu penyedap. Ia dipanggil ketika ada event besar, dikemas seadanya, disuruh tampil cepat karena “jadwal wisatawan padat”, lalu disuruh pulang dengan amplop sekadarnya—kalau tidak malah dengan ucapan terima kasih tanpa amplop. “Demi nama daerah,” kata mereka.
Ironis, bukan?
Di satu sisi, pemerintah begitu gencar menggaungkan jargon “melestarikan budaya lokal”, tetapi di sisi lain, yang dilakukan justru mematikan semangat kreatif para pelaku seninya. Tidak ada pembinaan yang serius, tidak ada peningkatan kualitas karya, tidak ada upaya memperkuat manajemen organisasi seni agar bisa bertahan dalam dunia yang makin komersial.
Yang ada hanyalah formalitas.
Pertunjukan yang asal jadi, panggung yang dibuat sekadar agar tampak “ada kegiatan budaya”, dan kesenian yang direduksi hanya sebagai penghias brosur wisata.
Ketika Seni Dijual per Kilogram
Inilah wajah baru seni di era pariwisata. Seni tidak lagi bicara tentang makna, nilai, atau spiritualitas. Ia diukur dengan berapa banyak wisatawan yang datang, berapa tiket yang terjual, dan berapa rupiah masuk ke kas daerah.
Seni yang dulu lahir dari pengalaman hidup masyarakat, dari doa dan ritual, dari cinta dan perjuangan, kini dijadikan “produk”. Ia dijual seperti barang dagangan.
Sebuah tarian sakral bisa dikemas menjadi pertunjukan lima belas menit agar pas dengan jadwal tur. Sebuah musik tradisional bisa disederhanakan nadanya agar mudah diterima telinga asing. Bahkan cerita rakyat yang penuh makna bisa diubah sedemikian rupa agar lebih “menarik” di media sosial.
Lama-lama, kita tak lagi tahu mana yang asli dan mana yang sudah dipoles. Kesenian kehilangan rohnya—karena orientasinya bukan lagi pada nilai, tetapi pada pasar.
Realitas di Lapangan: Sumenep Sebagai Cermin
Mari ambil contoh nyata di Sumenep. Kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini punya kekayaan seni yang luar biasa: topeng dalang, macopat, ludruk madura, sandur, musik saronen, hingga ragam ritual yang penuh makna. Tapi berapa banyak dari kesenian itu yang benar-benar dikembangkan secara serius?
Yang sering terjadi justru sebaliknya:
Kesenian hanya tampil ketika ada tamu dari luar daerah atau momen perayaan hari jadi. Setelah itu, senimannya kembali ke rutinitas, kadang tanpa tahu kapan lagi mereka akan dipanggil tampil. Tidak ada ruang latihan yang layak, tidak ada honor yang sebanding, bahkan tidak jarang mereka harus rogoh kantong sendiri demi tampil “mewakili daerah”.
Pemerintah, dengan segala sumber dayanya, seolah tak punya visi jangka panjang tentang bagaimana kesenian bisa bertahan. Padahal yang dibutuhkan seniman bukan sekadar panggung sesaat, tetapi sistem pendukung—dari pelatihan, promosi, hingga pembentukan jaringan antar-komunitas.
Namun yang terjadi:
Apresiasi dibungkam oleh birokrasi. Kreativitas dikalahkan oleh agenda protokoler. Dan kesenian berubah menjadi “proyek seremonial”.
Mengapa Seni Lokal Kalah?
Kalau kita jujur, akar masalahnya bukan cuma soal kurangnya dana, tapi juga karena kesenian tidak lagi ditempatkan di posisi terhormat. Ia dianggap pelengkap. Dianggap sekunder.
Ketika program pariwisata diluncurkan, yang dipikirkan pertama kali adalah pembangunan hotel, perbaikan jalan, promosi digital, branding tempat wisata. Sementara kesenian—yang semestinya menjadi jiwa dari pariwisata itu—justru diletakkan di pinggir.
Padahal, tanpa budaya lokal, pariwisata hanyalah foto pemandangan yang indah tapi kosong.
Orang tidak datang ke Sumenep hanya untuk melihat laut atau kastil tua; mereka datang untuk merasakan ruhnya, mendengar ceritanya, mencicipi suasana hidup masyarakatnya. Dan itu semua, hanya bisa dipancarkan lewat seni dan budaya yang otentik.
Tapi kalau yang mereka lihat hanya pertunjukan yang dibuat demi kamera, demi “konten”, maka nilai otentik itu lenyap. Budaya jadi tontonan, bukan lagi tuntunan.
Efek Domino: Dari Ekonomi ke Identitas
Ketika kesenian dipaksa menyesuaikan selera wisatawan, perubahan besar pun terjadi.
Masyarakat mulai menilai seni bukan dari makna, tapi dari potensi pendapatan.
“Yang penting laku,” begitu kira-kira logika yang berkembang.
Seniman muda pun enggan mempelajari kesenian tradisional karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi. Mereka lebih memilih menjadi pemandu wisata, membuka kafe di dekat pantai, atau menjual suvenir. Akibatnya, regenerasi mandek. Seni tradisi kehilangan penerusnya.
Bahkan, dalam beberapa kasus, pariwisata justru mendorong perubahan nilai sosial.
Budaya gotong royong bergeser menjadi kompetisi bisnis.
Nilai kesederhanaan tergantikan gaya hidup konsumtif.
Dan ruang-ruang publik yang dulu digunakan untuk latihan kesenian, kini beralih fungsi menjadi lahan parkir atau kios oleh-oleh.
Tak heran, banyak seniman lama yang merasa “asing” di tanah sendiri. Mereka yang dulu dihormati karena kemampuan berkesenian, kini dipandang sebelah mata. Seolah seni mereka sudah “usang”, tidak relevan, dan tidak menguntungkan.
Antara Pariwisata dan Kolonialisme Baru
Ada yang menyebut fenomena ini sebagai bentuk kolonialisme baru—bukan lewat penjajahan fisik, tetapi lewat ekonomi budaya. Wisatawan (dan juga pelaku industri pariwisata) datang dengan standar selera tertentu, lalu masyarakat lokal dipaksa menyesuaikan agar bisa “diterima”.
Akibatnya, budaya asli jadi kabur.
Upacara adat diubah jadwalnya agar cocok dengan kalender wisata.
Busana tradisional dimodifikasi agar lebih “instagramable”.
Dan lagu daerah disulap jadi remix agar bisa viral di TikTok.
Semua demi menarik perhatian pasar.
Tapi di sisi lain, masyarakat kehilangan arah tentang siapa mereka sebenarnya.
Tidak Semua Buruk: Ada Cahaya Kecil di Ujung Terowongan
Meski begitu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pariwisata bisa menjadi sahabat budaya—asal dikelola dengan bijak.
Bila dilakukan dengan perencanaan matang dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, pariwisata justru dapat menjadi sumber kehidupan bagi kesenian. Banyak daerah membuktikan hal itu: seni tradisional yang hampir punah bisa hidup kembali karena didukung pariwisata yang berbasis budaya, bukan sebaliknya.
Pariwisata yang sehat adalah yang menghargai seniman sebagai subjek, bukan objek.
Yang memberi ruang pelatihan, bukan sekadar panggung pertunjukan.
Yang memahami makna di balik ritual, bukan menjadikannya tontonan murah.
Di sinilah pentingnya peran pemerintah, lembaga budaya, dan komunitas lokal. Bukan hanya memfasilitasi, tapi juga membangun sistem: pendidikan seni yang kuat, promosi yang beretika, serta kebijakan yang berpihak pada seniman.
Harapan yang Masih Mungkin
Barangkali yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar wacana “melestarikan budaya”, tapi keberanian untuk menata ulang paradigma. Bahwa pelestarian bukan berarti mempertahankan bentuk, tetapi menjaga ruhnya agar tetap hidup dan relevan.
Seni harus diberi ruang untuk berkembang secara alami, tanpa tekanan komersial yang menyesakkan. Ia harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bukan sekadar tontonan bagi orang luar.
Pemerintah harus berhenti memperlakukan kesenian seperti alat dekorasi. Mereka perlu mendengarkan para pelaku seni—orang-orang yang tahu bagaimana mencipta, menjaga, dan menghidupkan kembali warisan budaya.
Dan masyarakat pun harus belajar menghargai kembali seni tradisi sebagai bagian dari identitas mereka sendiri. Karena tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dari kebudayaan yang perlahan mati di hadapan kita sendiri.
Catatan Akhir: Antara Wisata dan Kesadaran
Pada akhirnya, perdebatan tentang “pariwisata sebagai biang keladi runtuhnya kesenian lokal” bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana kita memahami arah perkembangan budaya di tengah modernitas.
Pariwisata bisa menjadi kawan, tapi juga bisa menjadi lawan.
Ia bisa menghidupkan, tapi juga bisa membunuh.
Semuanya tergantung pada niat dan cara pengelolaannya.
Kalau pariwisata dijalankan hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan aspek sosial-budaya, maka ia benar-benar menjadi biang keladi kehancuran seni lokal. Tapi jika dijalankan dengan visi kebudayaan yang kuat—yang memberi ruang pada keaslian, partisipasi, dan kesejahteraan seniman—maka ia justru bisa menjadi penopang.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadikan budaya sebagai alat promosi, dan mulai menjadikannya sebagai pusat orientasi pembangunan. Karena pariwisata yang berkelanjutan tidak bisa tumbuh di atas reruntuhan budaya. Ia hanya bisa hidup kalau seni, tradisi, dan manusia di dalamnya juga hidup.
Dan ketika itu terjadi, barulah kita bisa berkata bahwa pariwisata bukan lagi musuh kesenian, melainkan jembatan bagi peradaban.
🟡 Catatan ini bukan sekadar kritik, tapi juga ajakan: agar kita semua, baik pemerintah, seniman, maupun masyarakat, kembali menata hubungan antara “wisata” dan “budaya”. Karena bila seni mati, maka pariwisata kehilangan jiwanya; dan bila budaya hilang, maka tak ada lagi yang bisa dibanggakan selain foto-foto kosong di brosur promosi.
Pilihan