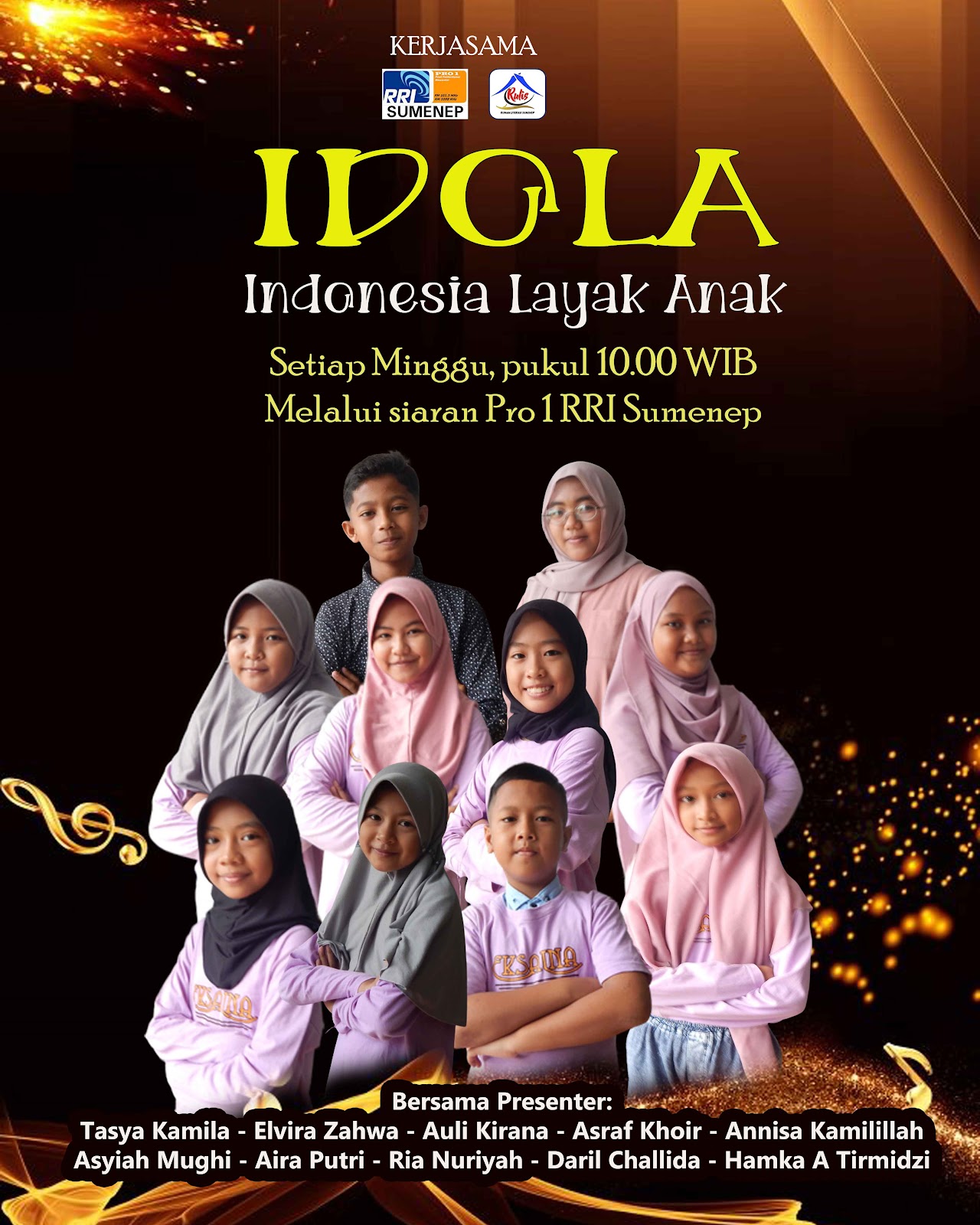Petani, Penyangga Peradaban yang Mulai Ditinggalkan Generasi Muda
Padi, Nasi, dan Jati Diri Bangsa
“Tanpa petani, kita kehilangan lebih dari sekadar nasi di piring; kita kehilangan jati diri sebagai bangsa.” Kalimat itu bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Pertanian bukan hanya urusan perut, melainkan urusan peradaban. Sebab sejak zaman nenek moyang, sawah dan ladang telah menjadi ruang hidup masyarakat Indonesia. Dari situlah tumbuh kebudayaan, tradisi, hingga sistem sosial yang kita kenal hari ini.
Namun, ironinya, di tengah gegap gempita modernisasi, profesi petani justru mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Anak-anak muda desa lebih memilih bekerja di kota sebagai buruh pabrik, pengemudi ojek online, bahkan pekerja migran di luar negeri. Menjadi petani dianggap identik dengan kemiskinan, kerja keras tanpa kepastian, dan masa depan yang suram. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang akan menanam padi, jika generasi muda tak lagi mau turun ke sawah?
Petani sebagai Penopang Peradaban
Jika kita menengok sejarah panjang umat manusia, pertanian selalu menjadi tonggak peradaban. Revolusi agrikultur ribuan tahun lalu memungkinkan manusia meninggalkan pola hidup nomaden dan membangun perkampungan permanen. Dari ladang-ladang sederhana, lahirlah kerajaan, kota, dan kebudayaan yang kompleks.
Di Indonesia sendiri, eksistensi petani begitu kuat. Padi bukan hanya makanan pokok, tetapi juga simbol spiritual dan kultural. Dewi Sri, dewi kesuburan dalam tradisi Jawa, menjadi lambang betapa sakralnya pertanian bagi masyarakat. Ritual wiwitan, slametan panen, hingga tradisi nyadran adalah cermin hubungan harmonis manusia dengan tanah, air, dan hasil bumi.
Sayangnya, nilai-nilai luhur itu kini perlahan memudar. Pertanian sering dipandang sebatas “mata pencaharian”, bukan lagi “way of life”. Padahal, jasa petani mencakup seluruh siklus kehidupan: mulai dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, mengendalikan hama, memanen, hingga menghadirkan makanan di meja makan kita. Tanpa mereka, tidak ada nasi, jagung, sayur, buah, atau bahkan kopi yang kita nikmati setiap pagi.
Petani yang Menua, Anak Muda yang Menjauh
Data menunjukkan, mayoritas petani di Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Artinya, regenerasi petani berjalan sangat lambat. Jika kondisi ini dibiarkan, 10–20 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis pangan akibat kekosongan tenaga kerja pertanian.
Mengapa anak muda enggan menjadi petani? Ada beberapa alasan utama:
- Citra Negatif Profesi Petani
Petani sering dianggap identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian. Hasil panen yang bergantung pada cuaca, harga jual yang fluktuatif, serta minimnya dukungan pasar membuat pekerjaan ini dipandang tidak menjanjikan. - Minimnya Akses Teknologi dan Modal
Pertanian masih banyak dilakukan dengan cara-cara tradisional. Padahal, generasi muda tumbuh dalam era digital yang serba cepat. Tanpa akses pada teknologi modern dan modal yang memadai, mereka merasa pertanian ketinggalan zaman. - Urbanisasi dan Modernisasi
Modernisasi membawa arus urbanisasi besar-besaran. Anak-anak muda desa lebih tertarik merantau ke kota yang dianggap menawarkan kehidupan lebih layak. Sawah dan ladang ditinggalkan, bahkan sering beralih fungsi menjadi perumahan atau pabrik. - Kebijakan yang Kurang Memihak
Tidak jarang, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, benih unggul, atau akses pasar yang adil. Harga gabah sering ditekan oleh tengkulak, membuat petani sulit menikmati hasil jerih payahnya. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa pertanian bukan pilihan masa depan.
Negeri Agraris yang Bergantung pada Impor
Ironi lain yang harus kita hadapi adalah kenyataan bahwa Indonesia, negeri dengan julukan “agraris”, justru sering bergantung pada impor pangan. Beras, gula, kedelai, bahkan garam—komoditas yang seharusnya bisa diproduksi sendiri—masih diimpor dalam jumlah besar.
Ketergantungan ini tidak hanya mengancam kedaulatan pangan, tetapi juga menurunkan semangat generasi muda untuk menekuni pertanian. Bagaimana mungkin mereka bangga menjadi petani, jika negara sendiri tampak kurang percaya pada kemampuan petaninya?
Menghidupkan Kembali Semangat Bertani di Kalangan Muda
Krisis regenerasi petani sebenarnya bisa diatasi, asalkan ada upaya serius dan komprehensif. Generasi muda tidak boleh hanya dipandang sebagai konsumen teknologi, tetapi juga harus diajak menjadi pelaku utama dalam revolusi pertanian. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:
- Modernisasi Pertanian
Anak muda identik dengan teknologi. Maka, pertanian harus dibawa ke ranah yang sesuai dengan karakter mereka: smart farming, pertanian presisi, drone untuk pemetaan lahan, sensor kelembapan tanah, hingga e-commerce untuk distribusi hasil panen. Dengan demikian, bertani tidak lagi dipandang “kuno”, melainkan sebagai profesi modern yang keren. - Pendidikan dan Literasi Pertanian
Kurikulum pendidikan, khususnya di daerah pedesaan, perlu memberi ruang lebih bagi literasi pertanian. Sekolah-sekolah bisa mengintegrasikan praktik bercocok tanam dengan pelajaran sains, teknologi, dan kewirausahaan. Kampus juga harus melahirkan lebih banyak agripreneur muda. - Akses Modal dan Pasar
Generasi muda sering terkendala modal untuk memulai usaha tani. Program kredit mikro, koperasi desa, hingga platform investasi pertanian berbasis digital bisa menjadi solusi. Selain itu, pasar hasil tani harus transparan dan adil, agar petani muda tidak lagi terjerat tengkulak. - Membangun Kebanggaan Profesi Petani
Perlu ada kampanye besar-besaran untuk mengubah citra petani. Mereka harus ditampilkan sebagai pahlawan pangan, penjaga peradaban, dan pejuang kedaulatan bangsa. Jika menjadi tentara membela negara adalah kebanggaan, maka menjadi petani yang memberi makan bangsa juga harus dihormati.
Petani sebagai Pahlawan Pangan Nasional
Dalam konteks kedaulatan bangsa, petani sesungguhnya adalah garda terdepan. Mereka memastikan pasokan pangan tetap ada, meski kita menghadapi pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan iklim.
Bayangkan jika seluruh petani berhenti bekerja sehari saja. Pasar akan kosong, harga pangan melambung, dan kehidupan sosial terguncang. Petani bukan sekadar profesi, melainkan fondasi keberlangsungan hidup manusia. Karena itulah, “jasa petani” meliputi seluruh rantai kehidupan, dari hulu hingga hilir. Mereka adalah pahlawan pangan nasional, meskipun jarang mendapat penghormatan sebagaimana mestinya.
Filosofi Tanah dan Benih: Pelajaran untuk Generasi Muda
Ada pelajaran mendalam yang bisa kita ambil dari petani. Mereka mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Menanam benih hari ini bukan untuk dipanen esok, melainkan untuk dipetik beberapa bulan kemudian. Petani percaya pada proses, pada kerja keras yang disertai doa.
Filosofi itu sesungguhnya relevan dengan kehidupan modern. Generasi muda yang kerap tergesa-gesa mengejar hasil instan perlu belajar dari ritme alam. Bahwa sesuatu yang bernilai membutuhkan waktu, kesungguhan, dan keuletan.
Kembali Menoleh ke Sawah
Pertanian bukan sekadar urusan dapur, melainkan urusan masa depan bangsa. Jika generasi muda terus menjauh dari sawah, maka kita akan menghadapi krisis yang lebih dalam daripada sekadar kekurangan pangan: krisis identitas dan kedaulatan.
Petani adalah penyangga peradaban. Mereka bukan pekerja kelas bawah, melainkan penjaga keberlangsungan hidup. Saatnya kita membangun kembali kebanggaan menjadi petani, memberi dukungan nyata pada mereka, dan mengajak generasi muda untuk kembali menoleh ke sawah.
Karena sesungguhnya, siapa pun kita hari ini—entah pejabat, pengusaha, dosen, atau mahasiswa—semua berdiri di atas jerih payah petani. Di balik setiap butir nasi yang kita kunyah, ada keringat yang mengalir, ada doa yang dipanjatkan, ada harapan yang ditanamkan. Dan tanpa petani, mustahil kita bisa menyebut diri sebagai bangsa yang berdaulat.
(Rulis)
Pilihan