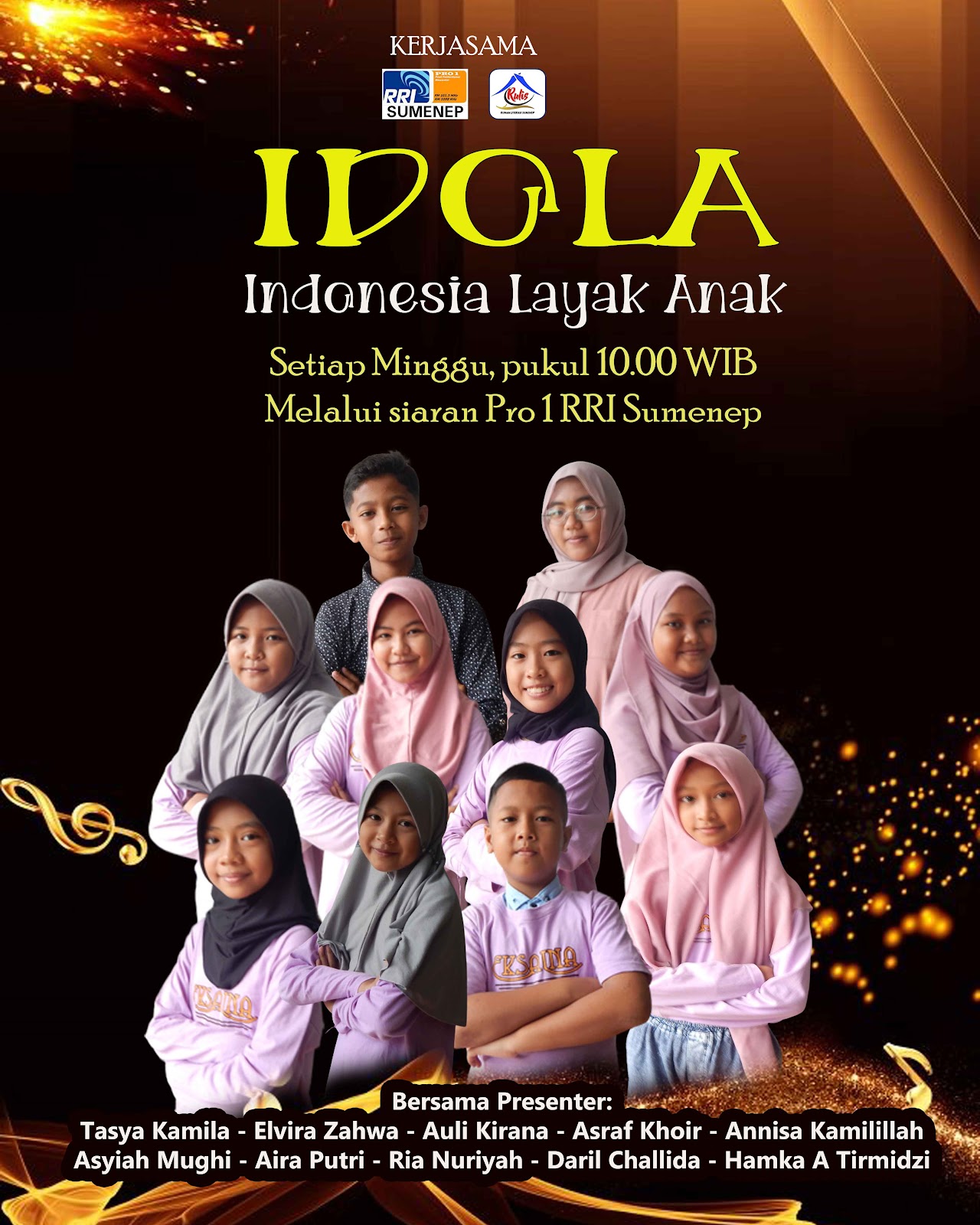Pariwisata Sumenep: Antara Eksploitasi dan Hilangnya Ruh Budaya

Pantai Salopeng Sumenep sekitar tahun 1990-an
Catatan Rulis
Selama ini, pemerintah gencar menggaungkan wacana pengembangan dunia pariwisata dengan menitikberatkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemajuan ekonomi kreatif masyarakat, terutama melalui sektor UMKM. Wilayah-wilayah yang dianggap strategis dijadikan etalase proyek pariwisata, seolah keberhasilan pembangunan diukur dari geliat ekonomi semata.
Padahal, hakikat pariwisata tidak hanya terletak pada dampak ekonomi, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kehidupan sosial dan budaya. Pariwisata sejatinya mampu memperkuat identitas lokal, melestarikan warisan budaya, membuka ruang pertukaran budaya, serta memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan autentik bagi wisatawan terhadap budaya masyarakat setempat.
Sayangnya, dimensi sosial-budaya ini kerap dinafikan. Ia justru dijadikan alat propaganda wisata, tanpa menyentuh akar budaya yang sesungguhnya. Tradisi, seni, dan kuliner lokal hanya dijadikan “hiasan acara”, bukan sebagai bagian yang hidup dan tumbuh dari masyarakatnya. Alhasil, eksplorasi budaya yang semestinya menggugah, justru menjelma menjadi eksploitasi budaya yang semata mempertimbangkan nilai ekonomi.
Di Sumenep, potensi peninggalan budaya begitu besar dan beragam. Namun, potensi ini justru mengalami degradasi — suatu kondisi ketika sumber daya yang menjanjikan mengalami penurunan nilai, kualitas, dan fungsinya. Alih-alih berkembang, banyak aset budaya justru kehilangan arah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kemampuan pemerintah membangun stimulan yang sehat bagi para pelaku dan kreator kesenian.
Contoh nyata dapat dilihat pada Lapangan Kesenian Sumenep, yang semula dibangun dengan semangat gotong royong sebagai ruang ekspresi seniman lokal. Kini, panggung megah itu tak lebih dari monumen mangkrak, menelan anggaran besar tanpa fungsi yang berarti. Hal serupa terjadi pada lapangan kerapan sapi, simbol budaya yang mulai kehilangan rohnya karena kurangnya perhatian serius dan pemahaman mendalam dari pemerintah terhadap nilai kesenian dan kebudayaan itu sendiri.
Ironisnya, lembaga resmi seperti Dewan Kesenian Sumenep — yang sejatinya menjadi motor penggerak kegiatan seni dan budaya — justru diberangus hanya karena perbedaan kepentingan politik. Akibatnya, upaya untuk membangkitkan kesenian Sumenep terhenti begitu saja. Naif dan menyedihkan.
Kini, gerakan pariwisata di Sumenep tak ubahnya pertunjukan yang diatur lewat remote control. Semua dikendalikan oleh kepentingan birokrasi, “orang dalam”, dan tim ahli yang hanya peduli pada keramaian sesaat. Sementara urusan hidup-mati dunia seni dibiarkan menjadi tanggungan para seniman sendiri.
Dampaknya sangat terasa: semangat berkesenian menjadi lumpuh, potensi budaya terpinggirkan, dan para seniman berubah menjadi apatis. Karya seni kehilangan makna dan esensinya sebagai ekspresi jiwa, refleksi budaya, dan hasil kreativitas yang otentik.
Lalu, pertanyaan yang menggantung dan tak bisa dihindari pun muncul:
Apa yang sebenarnya masih bisa diharapkan dari Sumenep, jika budaya hanya dijadikan komoditas, bukan jati diri?
(Rulis)
Pilihan