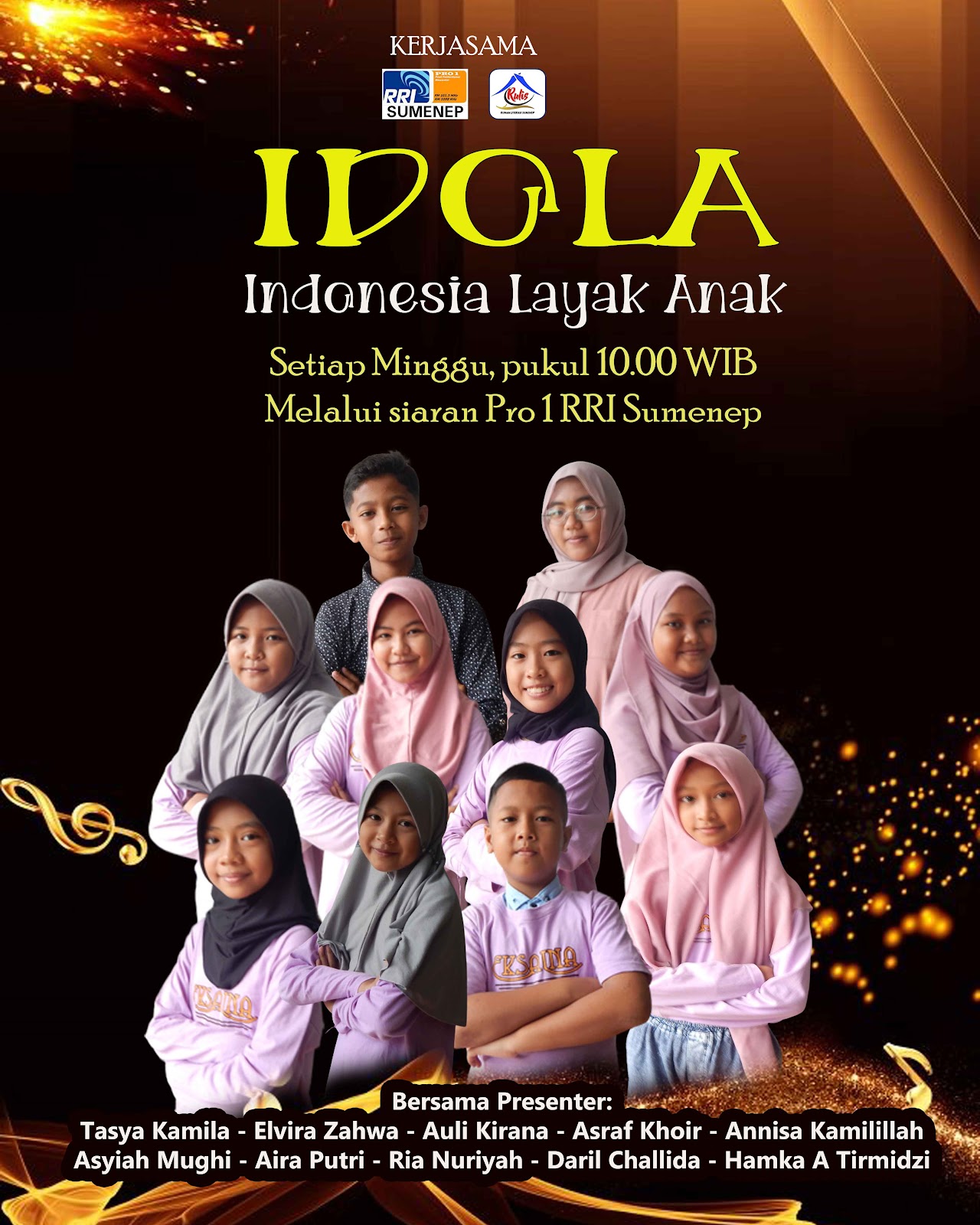Pengarang: Keren Tapi Kere
Oleh: Anindita S. Thayf *)
Adalah pengarang yang menyandang gelar “Mpu” pada zaman dahulu kala ketika abad raja-raja masih berkuasa. Merekalah yang mengarang kitab-kitab adiluhung seperti Pararaton, Nagarakertama, hingga Sutasoma dan sangat dihormati sebagai kaum cerdik cendekia. Posisi mereka sejajar dengan kaum brahmana. Kata-kata mereka, baik yang tersirat maupun tersurat, selalu menjadi rujukan bagi semua kasta masyarakat. Hingga zaman berubah, begitu pula nasib mereka. Kini, pengarang hanyalah kaum pekerja biasa dengan kemampuan khusus di bidang tulis- menulis.
Setelah era mpu berlalu, para pengarang disebut pujangga. Ada pujangga lama, ada pujangga baru. Mereka dianggap sebagai suara batin negerinya yang serta-merta menunjukkan keistimewaan posisi dan status mereka. Sebuah keistimewaan warisan dari etimologi kata pujangga yang bermakna kawan dekat raja, pendamping pangeran, dalam bahasa Sanskerta, bhujaṅga. Jelaslah, pujangga merupakan sebutan yang keren. Ia terkesan bersahaja sekaligus membumi sehingga mudah membayangkan seorang pujangga laksana resi rendah hati yang tinggal di menara tinggi.
Dalam perkembangan selanjutnya, pujangga kemudian berubah menjadi pengarang. Sebutan yang tetap terdengar bersahaja dan membumi, kecuali tanpa kesan elit karena sulit membayangkan seorang pengarang tinggal di menara tinggi. Perubahan zaman telah meruntuhkan menara tinggi sang pujangga dan menggantinya dengan sebuah rumah biasa-biasa saja atau sekadar kamar indekos sumpek sebagaimana yang dimiliki oleh “Manusia Kamar”-nya Seno Gumira Ajidarma.
Kendati tidak sementereng gelar pujangga, posisi pengarang pada hari ini tidak kalah keren. Dengan kemampuan mengarang, banyak pengarang kita berhasil pergi ke luar negeri berkat undangan dari berbagai program pendidikan dan budaya. Sebagaimana yang terjadi pascakemerdekaan, ada program STICUSA yang sangat murah hati kepada pengarang kita. Para pengarang senior., seperti Asrul Sani, Sutan Takdir Alisjahbana hingga Pramoedya Ananta Toer diundang datang ke Belanda untuk mengikuti program residensi selama beberapa bulan. Penyair-dramawan, W.S. Rendra dan Putu Wijaya, juga pernah menjalani residensi di Amerika Serikat selama beberapa waktu.
Ketika pemerintah menggalakkan program residensi sejenis pada tahun 2016, pengarang kita berbondong-bondong mendaftar demi merasakan pergi ke luar negeri secara cuma-cuma. Kesempatan ini jelas membuat posisi pengarang semakin keren, apalagi bila ditambah dengan kesempatan menjadi bagian dari dunia perfilman dan hiburan tanah air jika karya mereka dilirik oleh produser film, entah untuk dijadikan cerita utama atau sekadar selipan. Sejak itu, pengarang menjadi profesi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata sekaligus menjadi incaran banyak orang karena menawarkan kekerenan yang tidak memandang usia dan status, serta latar belakang pendidikan dan asal daerah.
Bambang Bujono, kritikus seni rupa, pernah mengatakan bahwa rubrik kebudayaan selama ini menumpang pada media massa. Menurutnya, hanya 3% pembaca yang melihat rubrik budaya sehingga kapan saja ia bisa ditutup. Inilah barangkali yang membuat majalah-majalah sastra kebudayaan seperti Zeniht, Sastra, Bintang Merah, Budaja Djaja hingga Horison bertumbangan satu per satu.
Di sisi lain, ada masa ketika majalah-majalah populer berjaya dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kreatif pengarang kita kala itu. Majalah-majalah ini, baik majalah remaja, seperti Aneka, Hai, Gadis, maupun majalah perempuan, seperti Femina dan Kartini, menyediakan tempat yang nyaman bagi pengarang untuk berkarya dan memulai karier sebagai pengarang. Selain majalah, koran juga menyediakan halaman khusus yang serupa.
Koran seperti Kompas menjadi tempat bagi pengarang untuk unjuk diri dan mengasah keterampilan sastrawinya. Kompas juga menyediakan rubrik untuk kajian-kajian kebudayaan yang memberi kesempatan kepada pengarang mengembangkan sayap kreativitasnya sesuai dengan wawasan dan pengalaman. Para penulis esai kebudayaan Kompas tentu pernah merasakan keasyikan menulis di rubrik Bentara yang menyediakan ruang tulis yang panjang dan honor yang lumayan besar. Koran lain, seperti Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos dan beberapa koran daerah, turut pula menunjukkan dukungannya kepada para pengarang dengan menyediakan ruang kreatif sejenis.
Setiap masa mestilah ada waktu habisnya. Pelan-pelan, rubrik sastra di majalah perempuan dan koran cetak memasuki senja kala. Jika pun ada yang masih bertahan, karya-karya yang dimuat di media tersebut hanya akan dibayar lebih sedikit daripada biasanya atau malah tidak lagi dibayar sama sekali. Memang, ada media digital yang mencoba mengambil alih peran majalah dan koran cetak dalam kehidupan pengarang dengan menyediakan tempat berkarya. Namun, pilihan tersebut kurang disambut baik karena sebagian besar pengampu media digital ternyata sama miskinnya dengan pengarang.
Alih-alih menghargai profesi pengarang, beberapa media digital justru meminta bantuan karya dan pengertian dari pengarang karena ketidakmampuan mereka menyediakan honor, tetapi mereka sangat membutuhkan konten bermutu untuk menggaet iklan dan pembaca. Untungnya, masih ada segelintir media digital yang berkenan menyediakan honor dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti Kalam Sastra, Tengara, dan satu-dua media milik perusahaan penerbit. Jumlahnya yang tidak banyak membuat tulisan masuk ke media-media digital baik hati ini mesti selalu berada dalam antrean konfirmasi yang panjang. Kondisi ini menantang pengarang untuk mempelajari satu keahlian baru, bersabar.
Pekerjaan pengarang adalah membuat karya, seperti novel, cerpen, esai atau naskah drama. Berbeda dari dosen yang mendapatkan gaji pokok dan tunjangan setiap bulan, penghasilan pengarang murni berasal dari hasil tulisan, misalnya, royalti buku. Biasanya, royalti dibayarkan oleh penerbit setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah buku yang terjual. Pendapatan dari royalti ini kemudian akan dipotong pajak sebesar 6% bagi yang memiliki NPWP. Selain honor menulis, inilah sumber penghasilan utama pengarang profesional yang sepenuhnya hidup dari mengarang.
Mirisnya, kehidupan pengarang seolah tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Majalah Intisari yang terbit pada tanggal 1 Oktober 1963 memuat tulisan berjudul “Dapatkah Penulis Indonesia Hidup dari Tulisannja?”. Dalam artikel ini disebutkan bahwa honor penulis hanya sebesar 500 rupiah kala itu. Menurutnya, jika seorang penulis bisa menulis dua karangan setiap minggu, ia akan mendapatkan penghasilan 4.000 rupiah per bulan.
Apa yang dialami oleh penulis tahun 1960-an ternyata masih terjadi sekarang. Masih ada tulisan yang dibayar dengan honor 20 ribu, bahkan banyak pula yang menghitungnya per jumlah viewers dan honor hanya bisa ditarik jika tulisan yang disetorkan telah melebih jumlah yang ditetapkan. Oleh karena itu, sungguh tepat kiranya tulisan “Dapatkah Penulis Indonesia Hidup dari Tulisannja?” mengutip pidato bung Karno yang sudah disesuaikan dengan keadaan penulis pada saat itu, “Penghisapan manusia jang satu (si penulis) oleh manusia jang lain (penerbit).”
Apa pun kondisinya, di sepanjang hidupnya yang tidak akan pernah mendapatkan tunjangan kerja atas karya-karyanya, apalagi tunjangan kesehatan atas profesinya. pengarang selalu bisa menghibur diri bahwa toh mereka menulis bukan untuk hidup, melainkan karena panggilan jiwa, kepuasan batin, laku iman, sekadar self healing, atau apa pun namanya. Yang pasti, honor tulisan dianggap tidak penting hanya jika isi dompetmu sudah dijamin oleh pekerjaanmu yang lain atau oleh orang lain.
*) Novelis dan esais
Tulisan ini telah dimuat di Harian Rakyat Sultra, 07/07/2025