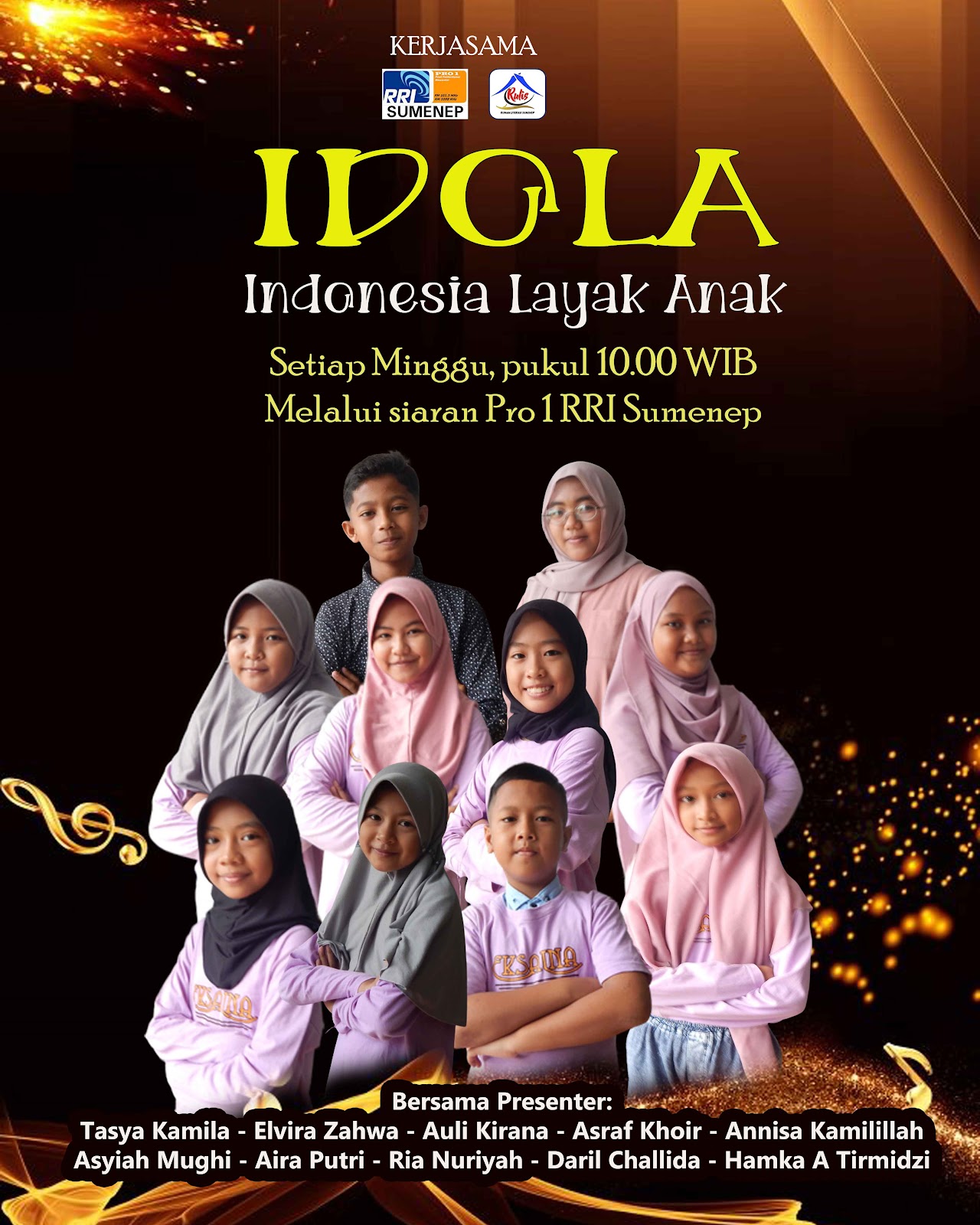Hamid Jabbar, Sang Penyair Zikir dari Ranah Minang
 |
| Hamid Jabbar saat membacakan puisi |
Hamid Jabbar lahir pada 27 Juli 1949 di Koto Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia tumbuh di tengah keluarga yang mencintai pantun dan tradisi lisan Minangkabau. Ibunya kerap bersenandung pantun dan zikir, menanamkan kepekaan bahasa dan irama dalam batinnya sejak kecil. Dari sanalah benih kepenyairan itu tumbuh — alami, tulus, dan penuh getar spiritualitas.
Masa remajanya dihabiskan di Sukabumi dan Bandung. Di sana, ia aktif dalam organisasi pelajar seperti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) pada tahun-tahun pergolakan 1960-an. Semangat idealisme muda itu kelak membentuk sikapnya sebagai penyair yang tajam dalam membaca realitas sosial, namun tetap lembut dalam bahasa dan iman.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Hamid merantau ke Jakarta. Ia bekerja sebagai wartawan di Indonesia Express dan Singgalang, kemudian menjadi redaktur di Balai Pustaka, serta mengabdikan diri cukup lama di majalah sastra Horison — wadah penting bagi penyair-penyair besar Indonesia. Ia juga aktif dalam kegiatan Dewan Kesenian Jakarta, menjadikan dirinya bukan hanya penyair di atas kertas, tetapi juga penggerak di dunia sastra.
Pada tahun 1975, ia menikah dengan Yulianis Zain, seorang sarjana muda Bahasa Arab dari IAIN Imam Bonjol. Dari pernikahan itu lahirlah dua putri, Meuthia Aulia Jabbar dan Lilla Aulia Jabbar, yang menjadi bagian penting dari kehidupan tenang di balik dunia kata dan zikir yang digelutinya.
Hamid Jabbar dikenal sebagai penyair yang sangat religius. Puisinya tak sekadar kata, tapi doa dan tafakur. Dalam setiap lariknya, terasa denyut spiritual yang berpadu dengan keprihatinan sosial. Ia menulis dengan kesadaran bahwa puisi bukan hanya keindahan bahasa, melainkan perjalanan jiwa menuju makna.
Karya-karyanya memantulkan perpaduan itu dengan jernih: Poco-Poco (1974), Dua Warna (1975), Wajah Kita (1981), dan yang paling monumental, Super Hilang, Segerobak Sajak (1998) — kumpulan 143 puisi yang merangkum perjalanan 25 tahun kepenyairannya. Dalam buku itu, Hamid menyingkap perenungan tentang Tuhan, manusia, dan dunia yang terus berubah. Puisinya seperti zikir panjang yang diselingi keluhan sosial, kadang getir, kadang pasrah.
Dalam puisinya Setitik Nur dan Zikrullah, misalnya, terasa betapa ia menulis bukan untuk kemasyhuran, melainkan untuk mengabdi pada kebenaran batin. Ia menjadikan puisi sebagai cara mengucap syukur dan juga sebagai alat menggugat nurani publik. Tidak berlebihan bila banyak kalangan menyebutnya sebagai “penyair zikir dan dangdut” — karena ia bisa membawa bahasa langit ke bumi, dan bahasa rakyat ke langit.
Ketekunannya di dunia sastra tidak berhenti pada menulis. Ia membina generasi muda, mendorong penulis pemula, dan aktif di berbagai forum sastra nasional. Ia meyakini, sastra adalah jembatan antara nurani dan realitas — ruang di mana manusia belajar menjadi manusia.
Puncak dedikasinya terjadi di akhir hayat. Pada 29 Mei 2004, di sebuah panggung Dies Natalis Universitas Islam Negeri Jakarta, Hamid Jabbar membacakan puisinya yang berjudul Merajuk Budaya Menyatukan Indonesia. Di tengah pembacaan itu, ia terhenti. Suaranya hilang. Tubuhnya rebah di atas panggung — dan di sanalah napas terakhirnya berhenti. Penyair itu wafat dalam posisi yang paling ia cintai: membaca puisi.
Kematian itu seakan menjadi penegasan bahwa hidup Hamid Jabbar memang seluruhnya untuk sastra. Ia menulis dengan hati, bekerja dengan puisi, dan meninggal dalam bahasa yang menjadi kehidupannya. Hingga kini, nama Hamid Jabbar dikenang sebagai sosok yang menjadikan sastra bukan sekadar karya, tapi laku hidup — sebuah zikir panjang dalam bentuk kata.
Merantau ke Jakarta
Sejak kecil, Hamid sudah terbiasa dengan pantun dan zikir—ibunya sering melantunkan pantun, menyemai rasa cinta terhadap bahasa dan irama dalam jiwanya. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Bandung, SMA jurusan Paspal. Namun, bukan sekadar sekolah yang membentuk dirinya: masa remaja sebagai pelajar perantauan di Sukabumi dan Bandung mempertemukannya dengan realitas kemiskinan, kondisi sosial yang timpang, dan protes-protes idealisme anak muda. Ia bergabung aktiv dalam organisasi pelajar, seperti KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), yang membukakan matanya akan dunia yang lebih besar dari kampung halaman.
Memasuki usia dewasa, Hamid memilih merantau ke Jakarta. Di ibu kota, ia menimang karier sebagai wartawan—Indonesia Express, Singgalang—lalu sebagai redaktur di Balai Pustaka, dan akhirnya sebagai Redaktur Senior di majalah Horison. Posisi-posisi ini bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi sebagai panggung: panggung untuk mengasah ketajaman pengamatan, memperluas jaringan sastrawan, dan meletakkan puisinya di tengah dinamika nasional.
Ia menikah pada 16 Februari 1975 dengan Yulianis Zain, seorang sarjana muda bahasa Arab. Kehidupannya di rumah tak jauh dari dunia batin: dua putri mereka, Meuthia Aulia dan Lilla Aulia, menjadi bagian dari keseharian yang sering kali melibatkan kata dan zikir.
Dalam puisinya, Hamid Jabbar selalu mencari titik temu antara bahasa manusia dengan lirihnya doa. Tema religius dan spiritualitas begitu kuat: zikir, tafakur, penantian, pertanyaan eksistensial tentang Tuhan dan manusia. Namun ia tak tinggal dalam keheningan doa semata: realitas sosial, ketidakadilan, dan kritik terhadap kekuasaan juga menapak kuat dalam puisinya. Gaya puisinya bervariasi — ada puisi lepas, ada kumpulan, ada yang pendek penuh getar, ada yang panjang gemuruh lirih.
Beberapa karya monumentalnya:
- Paco-Paco (1974)
- Dua Warna (1975)
- Wajah Kita (1981)
- Super Hilang, Segerobak Sajak (1998) — kumpulan yang merangkum lebih dari 25 tahun kepenyairannya.
Prestasinya diakui secara formal: ia mendapat Hadiah Yayasan Buku Utama atas Super Hilang, Segerobak Sajak, serta penghargaan seni dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Penyair Zikir dan Kritik
Karier jurnalistik membawanya ke Jakarta, di mana ia mengabdi sebagai wartawan untuk Indonesia Express dan Singgalang, lalu menjadi redaktur di Balai Pustaka, dan kemudian Redaktur Senior di majalah sastra Horison. Posisi-posisi ini bukan sekadar pekerjaan: bagi Hamid, mereka adalah ruang publik untuk mempertanyakan, meniupkan kritik, dan memperdengarkan suara batinnya melalui kata.
Kehidupan pribadinya secara sederhana menuntun: menikah pada 16 Februari 1975 dengan Yulianis Zain, sarjana muda Bahasa Arab, dan dikaruniai dua putri, Meuthia Aulia dan Lilla Aulia — yang menjadi saksi kecil dari pagi, malam, dan doa yang ditulis Hamid di rumahnya.
Karya-Karya Monumental & Tema Sentral
Hamid Jabbar menghasilkan sejumlah karya yang dianggap tonggak sastra Indonesia modern, terutama dari generasi 1970-an dan 1980-an. Beberapa karya paling menonjol:
- Poco-Poco (1974)
- Dua Warna (1975)
- Wajah Kita (1981)
- Super Hilang, Segerobak Sajak (1998) — kumpulan 143 sajak yang merangkum lebih dari seperempat abad karyanya.
- Puisi-puisi bebasnya seperti Setitik Nur, Zikrullah, Ketika Khusyuk Tiba Pada Tafakur Kesejuta.
Tema-tema sentral dalam puisinya umumnya berada di garis dua: kerinduan spiritual terhadap Tuhan dan kritik sosial terhadap penguasa atau ketidakadilan. Dalam Super Hilang, Segerobak Sajak, misalnya, Hamid menggunakan bahasa yang ekspresif, citra yang kadang simbolik, bentuk puisi yang variatif — dari yang pendek sampai panjang, dari yang sangat lirih sampai yang nyaring.
Peristiwa Akhir & Warisan
Warisan Hamid Jabbar dalam dunia sastra Indonesia adalah bahwa puisi bisa menjadi medium dialog: antara manusia dengan Tuhan, antara penguasa dengan rakyat, antara rasa takut dan harapan. Puisinya terus dibaca, dikaji, dan dipentaskan. Acara seperti peringatan tahunan wafatnya ia, baca puisi publik, atau diskusi sastra, membuktikan bahwa suara Hamid Jabbar tetap bernyawa dalam jiwa banyak orang.
Kutipan Puisi & Potongan Puitis
Berikut salah satu puisi pendek karya Hamid Jabbar yang bisa dijadikan sebagai kutipan penutup artikel:
Puisi: “Kembali”
Surat buat Kekasih, dikirimkan setiap hari: dengan tangan gemetar
Surat buat Kekasih, kembali ke tangan sendiri: alpa dan nanar!
Surat, diri sendiri, alpa dan nanar: remuk dalam postcard
Melayang dan melayang, luruh dan luruh: tak bisa lagi gemetar!
(1978)
(Dirangkum dari beberapa sumber)
Pilihan