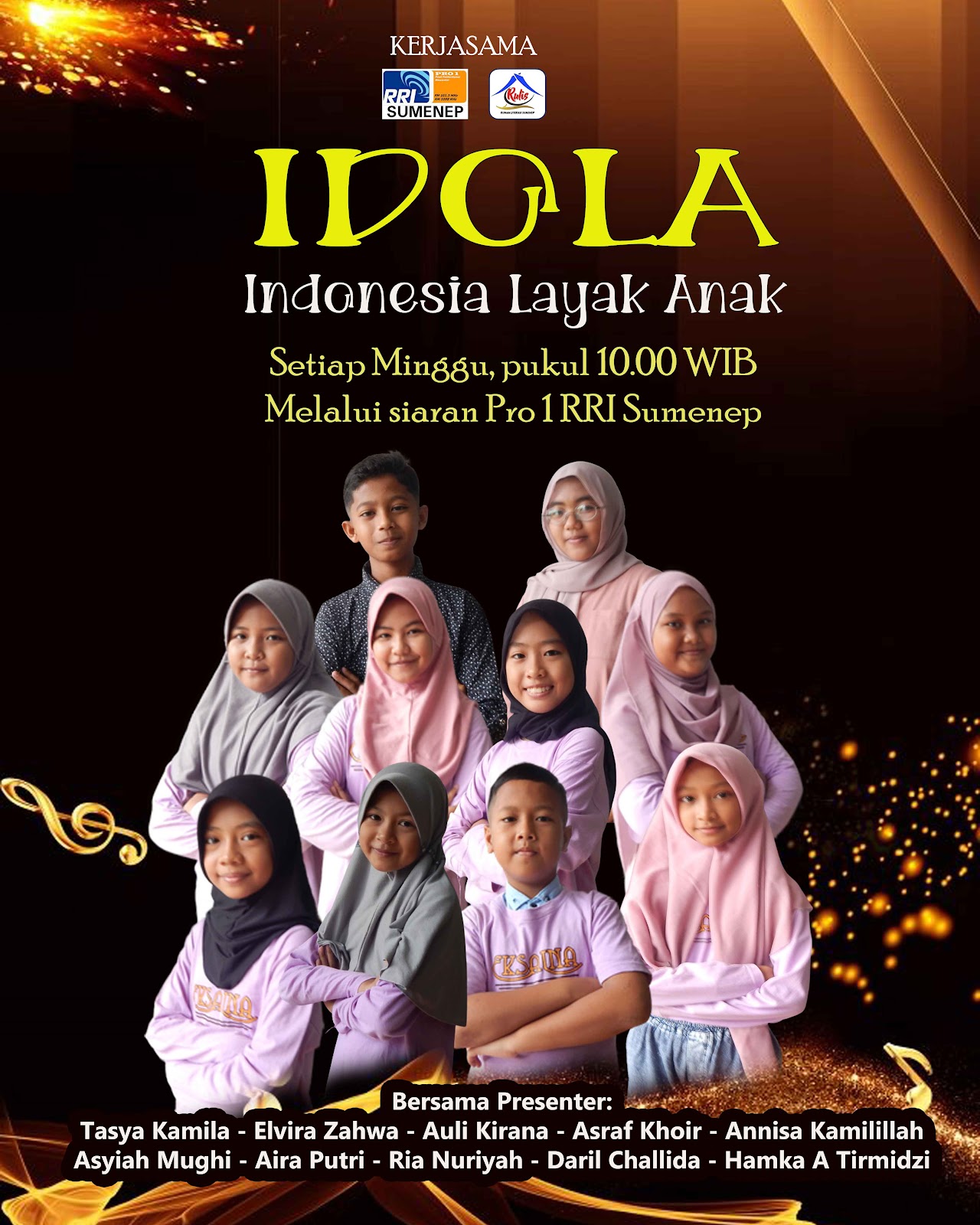W.S. Rendra: Sang Burung Merak dari Jagat Sastra Indonesia
 |
| WS Rendra saat membaca puisi |
Di tengah geliat dunia sastra Indonesia, nama W.S. Rendra berdiri megah seperti pohon tua yang rindang. Karya-karyanya menjadi tempat bernaung bagi kata, makna, dan perlawanan. Ia dikenal bukan hanya sebagai penyair, tetapi juga sebagai aktor, sutradara, sekaligus suara nurani bangsa. Rendra adalah sosok yang melampaui zaman — penyair yang tidak hanya menulis, tetapi juga menghidupkan kata-kata dengan seluruh jiwa dan tubuhnya.
🏡 Masa Kecil dan Lingkungan Keluarga
W.S. Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 7 November 1935 dengan nama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra. Ia berasal dari keluarga guru yang mencintai seni dan pendidikan. Ayahnya, R. Cyprianus Sugeng Broto, adalah guru Bahasa Indonesia dan Jawa di SMP Katolik Solo, sedangkan ibunya, Raden Ayu Catharina Ismadillah, seorang penjahit kebaya yang lembut dan religius.
Sejak kecil, Rendra tumbuh dalam suasana rumah yang sarat nilai budaya Jawa dan religiositas Katolik. Dari sang ayah ia belajar sastra dan bahasa, dari ibunya ia mengenal rasa keindahan dan kasih. Di usia yang masih belia, Rendra sudah akrab dengan cerita wayang, tembang, dan puisi Jawa. Ia sering menulis syair kecil dan membacakannya di hadapan teman-temannya di sekolah.
Lingkungan Solo yang kaya tradisi turut membentuk kepekaan artistiknya. Ia tumbuh di antara alunan gamelan, drama rakyat, dan ritual budaya Jawa — yang kelak menjadi warna khas dalam karya-karyanya.
🎭 Pendidikan dan Awal Ketertarikan pada Sastra
Rendra bersekolah di SMA St. Yosef Surakarta, tempat ia mulai aktif menulis puisi dan drama pendek. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke Jurusan Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Di kampus inilah Rendra mulai dikenal sebagai penyair muda yang berbakat.
Ia mendirikan kelompok teater dan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Tahun 1957, puisinya mulai dimuat di berbagai majalah sastra seperti Sastra, Budaya, dan Basis. Karya awalnya banyak bertemakan cinta dan kehidupan sehari-hari, namun sudah menunjukkan kekuatan bahasa dan emosi yang khas.
Rendra juga banyak membaca karya penyair dunia — Shakespeare, T.S. Eliot, dan Dylan Thomas — namun ia tidak meniru; ia menafsirkan dengan cara sendiri, mencampur spirit Barat dengan jiwa Timur. Dari situ, muncul gaya puitik yang khas, kaya metafora, dan berirama seperti lagu jiwa.
✈️ Perjalanan ke Amerika dan Pencerahan Spiritual
Pada tahun 1964, Rendra memperoleh beasiswa untuk belajar di American Academy of Dramatic Arts, New York. Di negeri asing itu, ia berkenalan dengan teater modern, puisi bebas, dan gerakan sosial. Ia belajar bagaimana seni dapat menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar hiburan.
Pengalaman di Amerika membuka cakrawala berpikirnya. Ia melihat kebebasan berekspresi dan bagaimana seniman bisa menjadi suara publik. Ketika kembali ke Indonesia tahun 1967, ia membawa semangat baru — semangat untuk menjadikan sastra dan teater sebagai alat pencerahan rakyat.
🌿 Kembali ke Tanah Air dan Lahirnya Bengkel Teater
Sekembalinya ke Indonesia, Rendra mendirikan Bengkel Teater di Yogyakarta pada tahun 1967. Bengkel ini bukan sekadar tempat latihan, tetapi laboratorium seni dan spiritualitas. Di sana, para anggota belajar berteater sambil menemukan jati diri dan kepekaan sosial.
Bengkel Teater melahirkan banyak seniman besar dan karya monumental. Pementasan-pementasannya tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah kesadaran sosial dan politik. Beberapa karya pentingnya antara lain:
- “Mastodon dan Burung Kondor” (1972)
- “Panembahan Reso” (1986)
- “Sekda” (1975)
- “Kisah Perjuangan Suku Naga” (1977)
Dalam setiap lakonnya, Rendra mengkritik kekuasaan yang menindas rakyat. Ia menampilkan realitas sosial dalam bentuk simbolik, menggugat ketidakadilan dan kemunafikan pejabat. Bahasa panggungnya penuh energi — perpaduan antara tradisi teater Jawa dan dinamika modern.
✊ Penyair yang Melawan dan Suara Nurani Bangsa
Selain teater, Rendra juga dikenal lewat puisi-puisi sosialnya yang tajam dan berani. Ia menulis puisi bukan untuk keindahan semata, tetapi sebagai jeritan nurani terhadap penindasan dan ketimpangan.
Kumpulan puisinya yang terkenal antara lain:
- Ballada Orang-Orang Tercinta (1957)
- Empat Kumpulan Sajak (1961)
- Blues untuk Bonnie (1971)
- Potret Pembangunan dalam Puisi (1979)
Dalam era Orde Baru, banyak puisinya dilarang karena dianggap mengkritik pemerintah. Ia bahkan beberapa kali ditahan karena sikapnya yang vokal terhadap ketidakadilan. Namun Rendra tidak pernah berhenti menulis. Ia percaya, seorang penyair harus berpihak pada kebenaran.
Ia pernah berkata:
“Penyair bukan tukang kata-kata, tapi saksi zaman.”
Kata-kata itu menjadi cermin dari seluruh perjalanan hidupnya.
❤️ Kehidupan Pribadi dan Spiritualitas
Rendra menikah dengan Sunarti Suwandi, rekan seprofesinya di teater, dan dikaruniai anak. Kemudian, ia menikah lagi dengan Ken Zuraida, yang juga aktif di Bengkel Teater. Dalam kehidupan pribadinya, Rendra dikenal religius dan memiliki perjalanan spiritual yang panjang — dari Katolik, kemudian memeluk Islam pada tahun 1970-an.
Perubahan keyakinan itu tidak mengubah sikapnya terhadap kemanusiaan; justru memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan Tuhan.
🌸 Akhir Hayat dan Warisan Abadi
Menjelang akhir hayatnya, Rendra banyak mengalami sakit. Namun semangat seninya tak pernah padam. Ia tetap menulis, mengajar, dan berbicara dalam berbagai forum sastra.
Pada 6 Agustus 2009, Rendra wafat di rumahnya di Depok, Jawa Barat, dalam usia 73 tahun. Indonesia kehilangan “burung merak” sastra — simbol kebebasan, keberanian, dan cinta pada kemanusiaan.
Jenazahnya dimakamkan di halaman rumahnya, dekat Bengkel Teater — tempat yang menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya dalam dunia seni.
✍️ Warisan Karya dan Pemikiran
W.S. Rendra meninggalkan warisan besar:
- Puluhan naskah drama dan kumpulan puisi,
- Gagasan bahwa seni harus berpihak pada rakyat,
- Dan teladan tentang kebebasan berpikir yang jujur dan berani.
Ia mengajarkan bahwa puisi bukan hanya tentang kata, tetapi tentang sikap hidup.
Dalam dirinya, seni dan perlawanan menyatu — menjadi api yang terus menyala dalam ingatan bangsa.
“Aku menulis bukan untuk terkenal,
tapi agar kata-kataku hidup di hati manusia.”
— W.S. Rendra
Pilihan