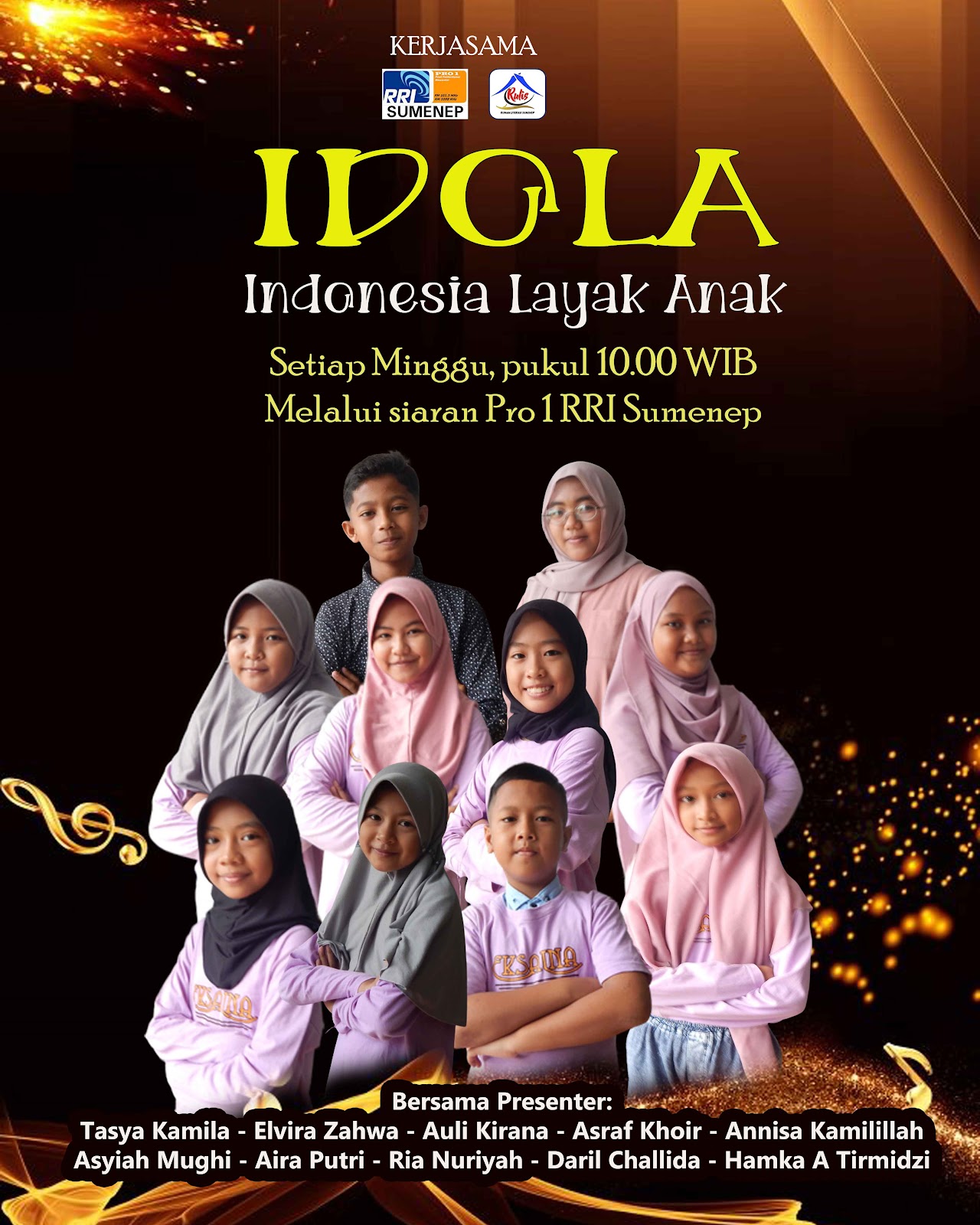Padána Dángdáng: Ketika Budaya Madura Mulai Lupa Suaranya Sendiri
Madura memiliki beragam parebasan—ungkapan tradisional sarat filosofi yang menjadi cermin cara berpikir dan bertindak masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang Madura masa kini yang mengenal, apalagi memahami, kekayaan bahasa dan budaya leluhurnya.
Budaya Madura kini bagai puing-puing sejarah: tercecer, berserakan, dan mulai tak dikenali. Zaman demi zaman—dari masa feodal, neofeodalisme, hingga era globalisasi—telah menggerus warisan itu sedikit demi sedikit. Pengaruh budaya luar masuk tanpa saringan, sementara akar budaya sendiri perlahan mengering.
Bahasa Madura pun ikut kehilangan kejernihannya. Di banyak tempat, ia bercampur dengan bahasa lain, kehilangan bentuk aslinya. Keadaan ini diperparah dengan semakin sedikitnya tokoh dan praktisi bahasa Madura yang masih aktif. Banyak yang telah wafat, dan yang tersisa pun sudah menua. Kurangnya referensi tertulis mengenai tradisi lisan juga membuat khazanah budaya ini semakin rapuh.
Lebih memprihatinkan lagi, para pelestari bahasa Madura sendiri belum satu suara. Bahkan soal ejaan pun belum ada kesepakatan. Perbedaan persepsi itu menjalar menjadi masalah yang lebih besar: bahasa dan budaya Madura seperti berhenti berkembang.
Padahal, di balik semua itu tersimpan satu kebenaran sederhana: bahasa dan budaya adalah identitas. Tanpa keduanya, Madura bisa kehilangan dirinya sendiri.
Belajar dari Parebasan: Cermin Hidup Orang Madura
Budaya Madura seharusnya diperkenalkan sejak dini. Salah satu jalannya adalah dengan menghidupkan kembali parebasan-parebasan klasik yang penuh makna filosofis.
Setiap peribahasa Madura adalah pelajaran moral, etika, dan kebijaksanaan hidup. Salah satunya adalah Padána Dángdáng — sebuah ungkapan yang dalam maknanya sekaligus menyentuh.
Menurut cerita lama orang Sumenep, dángdáng atau burung gagak dahulu dikenal sebagai burung yang bersuara merdu dan berjalan dengan anggun. Namun, karena sering meniru suara dan langkah binatang lain, lama-kelamaan dángdáng lupa pada dirinya sendiri. Suaranya berubah serak, langkahnya pun tak lagi indah.
Itulah simbol orang yang kehilangan jati diri karena terlalu sibuk meniru orang lain. Dalam konteks budaya, Padána Dángdáng menggambarkan masyarakat yang melupakan akar budayanya sendiri, terseret arus modernitas hingga tak mengenali siapa dirinya.
Parebasan Lain: Embi’ Kacang dan Embi’ Dhumbhá
Dalam pelajaran Bahasa Madura, sering mengingatkan siswanya tentang pentingnya memahami makna di balik parebasan kuno. Salah satunya berbunyi:
“Mon baghus pabágas, mon soghi pasoghá’, mon kerras akerrès.”
Ungkapan ini mencerminkan karakter khas orang Madura yang menjunjung kebaikan, kerja keras, dan ketegasan.
Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan adanya fenomena Padána Embi’ Kacang — seperti kambing kecil yang suka menyalahkan orang lain tapi tak mampu berbuat apa-apa ketika diberi tanggung jawab.
Menurut Baisuni, sifat Embi’ Kacang kini makin sering muncul: orang mudah mengkritik, merasa paling tahu, tetapi enggan turun tangan menyelesaikan masalah. Ironisnya, peribahasa ini bukan fenomena baru; ia adalah refleksi sifat manusia yang sudah dikenal sejak zaman dulu.
Sebaliknya, leluhur Madura juga mengenal sifat yang baik dalam peribahasa Padána Embi’ Dhumbhá. Kambing besar ini digambarkan tenang, tidak banyak bicara, namun bisa diandalkan dalam segala keadaan. Disuruh memimpin bisa, menjadi anak buah pun loyal. Sosok seperti inilah yang disenangi banyak orang—bijaksana tanpa banyak kata.
Madura dan Tantangan Modernitas
Melestarikan budaya bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia adalah cara menjaga identitas dan martabat bangsa. Akan menjadi ironi besar bila sejarah dan sastra Madura kelak lebih dikenal melalui tulisan orang luar ketimbang dari tangan putra daerah sendiri. Saat masyarakat Madura belajar tentang budayanya dari sumber asing, di situlah peribahasa Padána Dángdáng benar-benar menjadi kenyataan.
Budaya Madura tak boleh berhenti di museum, atau sekadar jadi catatan kaki dalam sejarah. Ia harus kembali hidup di sekolah, rumah, dan ruang publik. Harus kembali diucapkan, ditulis, dan dihayati—agar suara Madura tidak serak seperti dángdáng yang lupa cara bernyanyi.
Menemukan Suara yang Hilang
Perubahan zaman adalah keniscayaan, tetapi kehilangan jati diri bukanlah keharusan.
Melalui parebasan dan bahasa, orang Madura bisa menemukan kembali “suara” yang dulu indah—suara kebijaksanaan, kesantunan, dan kemandirian.
Sebab, selama masih ada yang mau menyebut dan memahami makna Padána Dángdáng, Embi’ Kacang, dan Embi’ Dhumbhá, selama itu pula roh budaya Madura masih hidup.
( Red. Rulis )
Pilihan