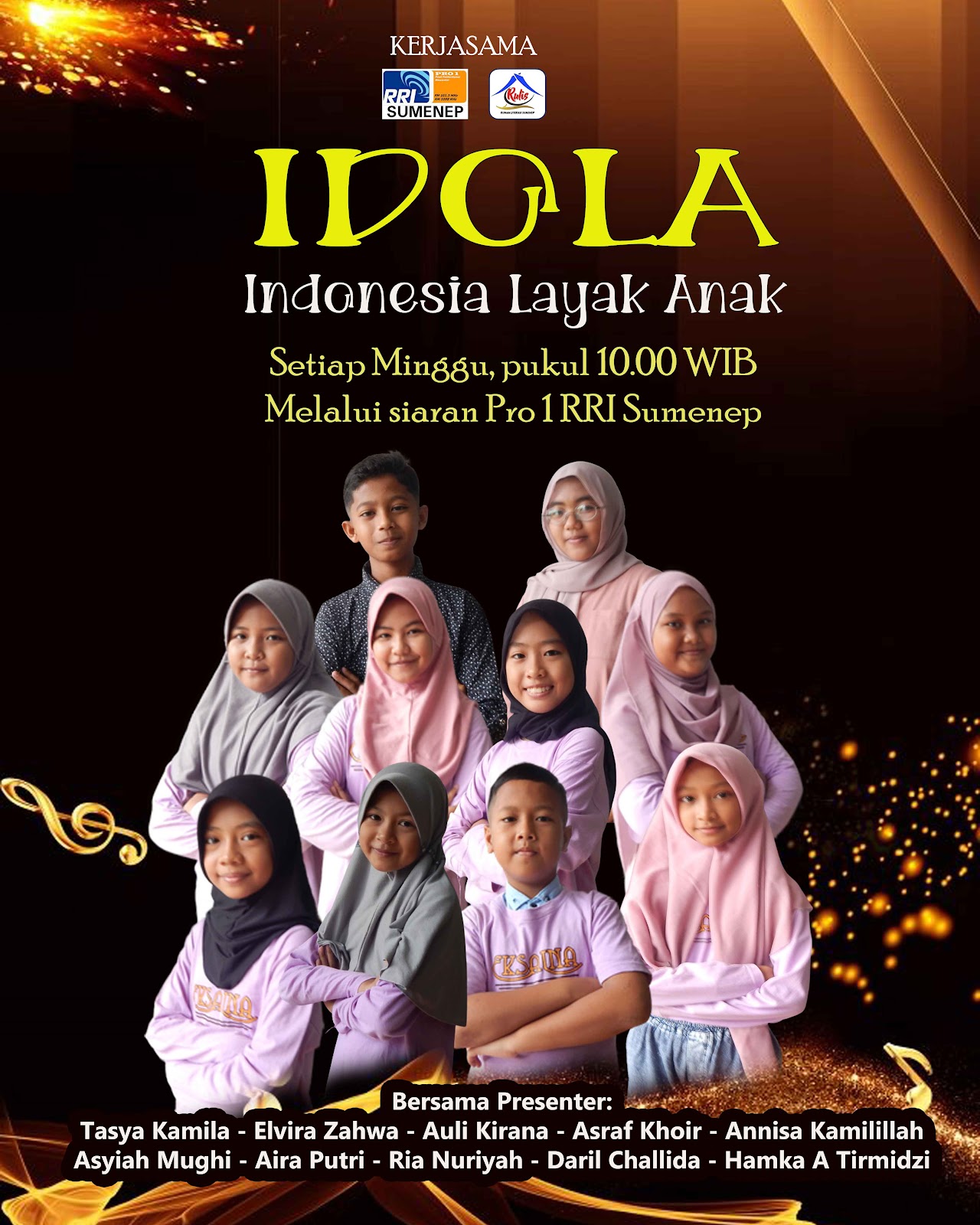Sedikit Tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal Madura
Syaf Anton Wr
Masyarakat Madura sudah sepatutnya untuk kembali pada jati diri dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya lokal. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif kearifan lokal.
Untuk itu, sebuah ketulusan, memang, perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur masyarakatnya. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari warga yang sama.
Para elit di berbagai tingkatan perlu menjadi garda depan, bukan dalam ucapan, tapi dalam praktis konkret untuk memulai; kearifan lokal yang digali, dipoles, dikemas dan dipelihara dengan baik yang nenatinya bisa berfungsi sebagai alternatif pedoman hidup manusia Madura dewasa ini dan dapat digunakan untuk menyaring nilai-nilai baru/asing agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Khalik, alam sekitar, dan sesamanya.
Persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan kearifan lokal untuk membangun karakter di masyarakat? Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi budaya lokal (kearifan lokal) yang relevan untuk membangun karakter. Hal ini dikarenakan kearifan lokal pada gilirannya akan mampu mengantarkan masyarakat untuk mencintai daerahnya.
Kecintaan masyarakat Madura pada daerahnya akan mewujudkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan warganya untuk menata diri sesuai dengan konsep yang diyakini kebenarannya dengan jiwa yang tangguh, semangat yang tinggi, serta dengan cara memanfaatkan alam secara bijaksana.
Dalam konteks tersebut, kearifan lokal menjadi relevan. Generasi muda Madura sudah sewajarnya diperkenalkan dengan lingkungan yang paling dekat di desanya, kecamatan, dan kabupaten, setelah itu tingkat nasional dan internasional. Melalui pengenalan lingkungan yang paling kecil, maka kita bisa mencintai desanya.
Apabila mereka mencintai desanya mereka baru mau bekerja di desa dan untuk desanya. Kearifan lokal mempunyai arti sangat penting bagi anak kita kelak. Dengan mempelajari kearifan lokal kita akan memahami perjuangan nenek moyangnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Nilai-nilai kerja keras, pantang mundur, dan tidak kenal menyerah perlu diajarkan pada anak-anak kita. Sebagaimana terungkap: karkarkar colpe’, abanteng tolang seang are seang malem, sapa atane bakal atana’, sapa adaghang bakal adaghing, barentheng, abanthal omba’ asapo’ angin, alako barra’ apello koneng dll.
Bila kerja banyak menghasilkan untung sehingga menjadi kaya, jangan lupa yang miskin atau tidak mampu, karena yang kaya berkewajiban menjadi tulang punggung yang miskin, mon sogi pasogha’ , jangan raja ghuntorra tada’ ojhanna
atau menjadi keras ta’ akerres. Untuk itu dalam menjaga martabat keluarga atau kelompok jangan sampai jha’ mettha’ buri’ etengnga lorong, sebab sapenter-penterra nyimpen babathang paste e kaedhing bauna.
Tentang tatakrama atau budi pekerti disebut sebagai Oreng andhi’ tatakrama reya akantha pesse singgapun, ekabalanja’a e dimma bhai paju, dan sebaliknya yang tidak berbudi disebut ta’tao Judanagara (Judanegara adalah seorang tumenggung di Madura yang sangat baik budi pekertinya, sehingga pantas dijadikan kaca kebbang (contoh teladan) bagi orang yang lain. Orang yang disebut tidak mengenal (ajaran) Judanegara dianggap jauh dari sikap mulia, alias hina)
Andhap asor tampaknya menjadi tolok ukur dalam menanamkan etika dan estetika, termasuk didalamnya tentang kesantunan, kesopanan, penghormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya sehingga menjadi raddin atena, bagus tengka gulina. Untuk membangun kebersamaan dalam saloka diungkap bila cempa palotan, bila kanca taretan, untuk menjaga keutuhan persabatan perlu dijaga mon ba’na etobi’ sake’ ja’ nobi’an oreng.
Andhap asor mensyaratkan kesantunan, kesopanan, penghormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang harus dimiliki orang Madura. Sehingga bagi orang Madura orang itu tidak dinilai dari segi luarnya tapi hatinya seperti ungkapan raddin atena, bagus tengka gulina. Atau pantun seperti di bawah ini:
Ba’ omba’ tana balina
Tana temor paseseran
Ba’jhuba’ teppa’ ghulina
Panda’ omor ker-pekkeran
Kehidupan yang harmoni menjadi penekanan kehidupan yang diharapkan dalam rampa’ naong beringin korong, serta ghu’tegghu’ sabbhu’ atau song-osong lombhung, merupakan solidaritas sosial antar warga.
Meski kekerasan kerap menjadi indentitas orang Madura seperti carok misal, dalam pandangan orang Madura memiliki tempat tersendiri, karena alasan-alasan tertentu karena perasaan malo akibat harga diinjak-injak sehingga melahirkan carok. Ango’ potea tolang etembhang pote mata atau otang pesse nyerra pesse, otang rassa nyerra rassa, otang nyaba nyerra nyaba yang barangkali menjadi pertimbangan mereka.
Sebenarnya semua itu dapat diselesaikan dengan terhormat bila diawali dengan bhak-rembhak yang sebenarnya mengakar kuat dalam masyarakat Madura.
Contoh diatas merupakan bagian kecil dari pendidikan karakter masyarakat melalui kearifan lokal, yang seharusnya telah dikenal dan atau diperkenalkan dari generasi ke generasi. Karena pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup.
Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Madura
Yang dimaksud dengan revitalisasi budaya lokal adalah kegiatan yang memungkinkan budaya lokal itu mampu menjawab tantangan jaman, tantangan hidup hari ini dengan menjadikan gantang penakarnya memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut yang menyusul langkah pelestarian alias pendataan (pendaftaran) dan pengenalan hasil budaya angkatan-angkatan terdahulu guna melawan lupa dan memulihkan ingatan kolektif suatu komunitas masyarakat.
Dengan demikian angkatan hari ini tidak menjadi angkatan lepas akar atau angkatan kosong. Jika terhenti hanya sebatas pelestarian dan menganggap budaya lokal sebagai buah karya angkatan-angkatan sebelumnya, maka dihawatirkan komunitas masyarakat akan hidup menyeret diri mundur ke masa silam sehingga kian tergenang di lumpur keterpurukan total. Dengan menganggap budaya silam itu yang paling sempurna dan berlaku di segala jaman.
Kenyataannya, karya-karya budaya masa silam tidak semuanya tanggap zaman dalam artian mempunyai daya guna untuk memecahkan masalah-masalah kekinian. Karena itu ia patut ditepis mana yang tanggap dan mana yang sudah kedaluarsa.
Yang kedaluarsa cukup catat saja menjadi sejarah, simpan di museum sebagai bandingan dan pelajaran, sebagai bagian dari sejarah dari mana kelak bisa melihat perkembangan diri sebagai suatu komunitas. Untuk menilai kedaluarsa tidaknya suatu hasil budaya, tentu yang jadi ukurannya adalah kemampuan nilainya menjawab tantangan hari ini.
Suatu penampilan bentuk sampai hakikat sehingga bisa menyebutnya tanggap atau tidak, tentu perlu perangkat yang seimbang, perlu analisis dan kajian tingkat relevansinya, sehingga nantinya dalam menentukan sikap budaya, tidak terperangkap sikap apriori.
Contoh misal; falsafah (budaya Madura): bapa’ babu’ guru rato dapat dipahami sebagai wilayah yang disakralkan, karena didalamnya banyak mengajarkan nilai etika dan estetika dalam perilaku kehidupan di masyarakat.
Namun dalam satu sisi, ada pihak menyebutnya sebagai bentuk pengebirian, karena akan membatasi keleluasaan melakukan tindakan dalam sebuah sistem di masyarakat. Demikian pula dengan falsafah abantal omba’, asapo’ angen; lebih bagus pote tolang, etembang pote mata, dan seterusnya, semua mempunyai nilai dan makna, namun tidak semua pula dapat diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini.
Lalu apa gerangan yang terjadi dari fenomena tersebut? Persoalannya sekarang, bagaimana dalam memilah sisi mana yang tanggap jaman, dan sisi mana pula sudah tidak patut lagi dikembangkan oleh masyarakat etnik Madura.
Nilai-nilai lokal tersebut dicari relevansinya dan diterapkan pada sarana baru kekinian. Perihal sarana inipun kiranya patut memperhatikan sarana yang sejak lama ada di dalam masyarakat, yaitu institusi masyarakat sebagai kekuatan masyarakat yang nantinya menjadi intrumen penggerak melalui kekuatan dasar piramida masyarakat.
Dengan menggunakan (memanfaatkan) budaya lokal untuk menjawab tantangan kekinian dan keterpurukan, ini juga merupakan ujud kongkrit dari revitalisasi budaya lokal.
Komunitas Lokal Madura Sebagai Aktor
Istilah pemberdayaan mungkin mengesankan bahwa komunitas Madura sekarang dalam keadaan tidak berdaya atau terpuruk. Istilah ini melukiskan keadaan yang negatif dan ada yang ingin diubah. Untuk mengubahnya, pertama dan terpenting adalah komunitas itu sendiri sebagai faktor intern pemberdayaan.
Pemerintah, komunitas masyarakat, baik didalam maupun dari luar atau siapapun tidak bisa menggantikan peranan komunitas itu sebagai aktor pemberdayaan. Karena pemberdayaan (kemudian pembangunan) yang bergulir bukanlah buah derma (hadiah). Jauh sebelumnya, kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi tradisi, semangat mandiri, berprakarsa, dan semangat gotong royong (song-osong lombung) ini sangat kuat di kalangan masyarakat Madura.
Membangun sebuah rumah, pemilik tidak repot lagi mencari tukang bangunan, material, dan bahkan suguhan, para tetangga dan kerabat keluarga tanpa pretensi apapun telah mempersiapkan segalanya.
Demikian pula aktifitas-aktifitas lainnya, yang semuanya mengarah pada kekuatan dasar masyarakat, yang mandiri, yang madani.
Menghidupkan kembali ingatan kolektif terhadap hal tersebut salah satu metode melalui pendekatan budaya merupakan usaha yang signifikan. Melalui dialog budaya, yaitu bagaimana mengembalikan suku, etnik dan masyarakat Madura, kembali menjadi komunitas-komunitas lokal, menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang luhur.
Untuk itu, pendidikan pembebasan melalui proses penyadaran akan menjadi kunci dan bisa dilakukan melalui pemaduan usaha-usaha produktif guna menjawab persoalan hari-hari yang kongkrit, dengan tanpa melupakan, bahwa usaha produktif ini merupakan bagian integral dari proses penyadaran dan pembebasan diri komunitas dari jebakan-jebakan globalisasi budaya.
Penyadaran diri tidak cukup hanya dengan mempersoalkan dan memperbincangkan semata, tapi bagaimana membangun jati diri masyarakat dan mengaktulisasikan dalam realitas kehidupan nyata.
Sebab kenyataan yang terjadi, fungsi dan peran masyarakat dalam artian membentuk kekuatan budaya telah dieksploitasi oleh kecenderungan yang bersifat material, sementara budaya (daerah, lokal dan tradisional) yang lebih mengacu pada konsep kehidupan bersama, tenggang rasa dan gotong royong itu, hampir kehilangan maknanya.
Bila fungsi tersebut lumpuh, apa yang diharapkan dari gerakan kekuatan budaya Madura sendiri?, kecuali secara lambat lauin masyarakat Madura akan kehilangan budaya Maduranya. Atau dengan kata lain tentu tak seorangpun mau menyatakan diri sebagai Malin Kundang. (Syaf Anton Wr)
Pilihan