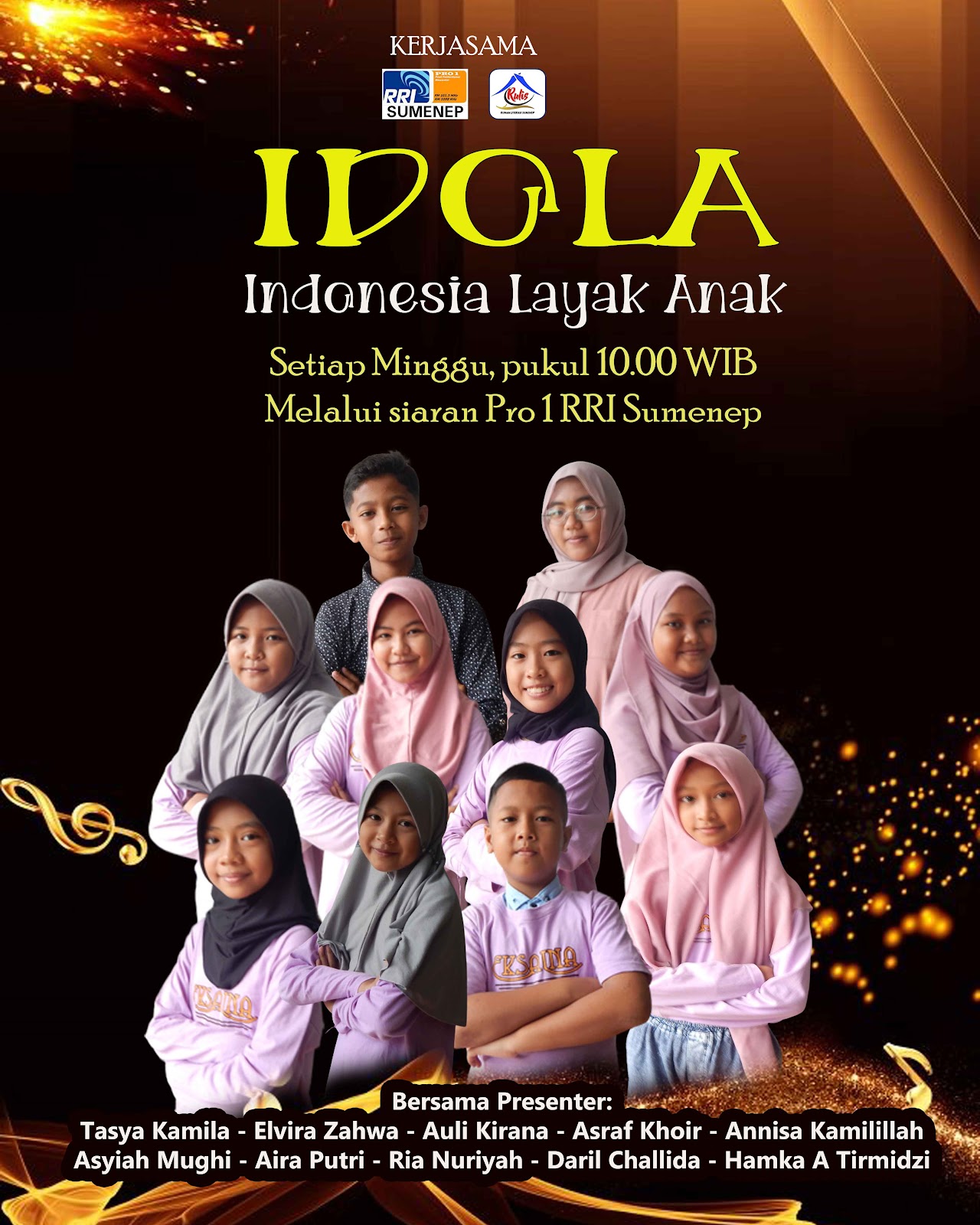Lebaran Sastra: Menggincui Madrasah dengan Puisi
Oleh: Masmuni Mahatma
Puisi dan perjalanan panjang histori Islam ikut membentuk tradisi ajarannya di berbagai wilayah dan masyarakat. (Mungkin) puisi dan tradisi ajaran Islam, adalah "saudara kembar." Senapas dan seirama.
Bukan tanpa alasan. Jika melihat awal ke-hadiran Islam, terutama masa Nabi Muhammad SAW di Hejaz 14 abad lalu, puisi, syair, dan berbagai bentuk ungkapan yang menunjukkan keindahan bahasa adalah entitas yang begitu populer di masyarakat. Puisi secara khusus memiliki popularitas yang setara dengan musik dan media sosial pada era kita. Mereka yang puitis, mereka yang memiliki kefasihan, mereka yang mempunyai kemampuan untuk merasakan keindahan (ber) bahasa, bagi masyarakat Arab saat itu dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan luhung dan ditakdirkan menjadi suci (Stetkevych, 1993; Allen, 2005).
Bahkan kalau becermin terhadap eksistensi Jalaluddin Rumi, seperti ditayangkan lebar-lebar oleh Reynold A Nicholson (1993), puisi telah lama dijadikan media luhur mentransformasikan ajaran dan pengalaman kesufian, salah satu inti "pengetahuan" dan "keagamaan" dalam Islam. Ini konstruksi pengetahuan, ajaran, dan tindakan keagamaan Islam yang tidak pernah ringan. Terutama Yang Mengenal Dirinya, Yang Mengenal Tuhannya, buku terjemahan dari Signs of The Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi, diterbitkan di Kuala Lumpur, Malaysia hingga Indonesia (2000), juga Fihi Ma Fihi, yang diinggriskan menjadi Discourse of Rumi, diterjemahkan A. J. Arberry, Inilah Apa Yang Sesungguhnya (2002), telah menarik dan menempatkan puisi sebagai medium transformasi kesufian. Tak berlebihan bila dalam tradisi Islam, puisi dan kesufian juga diibaratkan "pasangan harmonis" yang dianugerahkan.
Puisi dan keindahan narasi begitu dipuja dan dikagumi sebab ungkapan di dalamnya seolah memanifestasikan hal yang subtil dalam diri. Suatu perasaan yang terwakili atas kelembutan hati di tengah realitas hidup yang keras di tanah yang tandus. Syair-syair karya Imru ibn al-Qais (w. 565 M), seorang pujangga Arab pra-Islam, misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat Arab saat itu sudah memiliki tradisi sastra yang begitu luhur (Stetkevych, 1993). Bacalah salah satu syairnya yang berbunyi: "Seakan diriku, pada pagi perpisahan, saat mereka menjauh di pepohonan samur itu, laiknya pemetik hanzhal yang keruh." Atau pada ungkapan berikut: "Janganlah karena duka kau redup dan tampilkan yang indah Padahal obatku hanyalah air mata yang tercurah Maka adakah harapan pada usangnya bekas-bekas rumah?"
Tidak salah jika Nabi Muhammad akhirnya diutus dengan mukjizat Al-Qur'an, satu teks yang tercipta dari kalam Tuhan sebagai pedoman. Al-Qur'an hadir dengan bahasa yang mengatasi keindahan syair-syair pujangga Arab masa itu. Ia tidak saja secara kebahasaan memang tersusun dengan struktur istimewa, tapi juga mengandung makna yang tidak akan pernah susut tafsiran atasnya. Tentu Al-Qur'an bukan satu antologi puisi pada zamannya, namun bahasa Al-Qur'an yang menandingi keindahan syair dan berhias unsur struk-tural penuh makna, membuat kitab ini tak ubahnya "karya sastra" yang agung. Al-Qur'an bisa merangkum hait-bait dengan rima yang tak jenuh untuk dibaca. Pada beberapa tempat, Al-Qur'an juga tidak ragu untuk menuturkan kisah layaknya novel, dengan pengulangan (refrein) dan leksikalitas yang berbeda, kerumitan dan irama, diksi dan metafora, atau perangkat-perangkat sastra lain, Nabi Muhammad pun berulang kali dituduh sebagai tukang tenung (QS. 74:24; 69:42; 6:7; 10:2), sebab Al-Qur'an yang dibacakan layaknya sihir bagi ma-syarakat Arab yang mendengarnya.
Al-Qur'an yang dibaca dan dibacakan, dengan makna yang begitu jelas namun juga terkadang memanggil orang untuk menafsirkan, pada gilirannya memberikan ilham tersendiri bagi sahabat Nabi, ulama, dan para penulis muslim kemudian. Ali ibn Abi Thalib ra., sahabat Nabi kenamaan dan khalifah keempat umat Islam, misalnya, terbiasa membuat ungkapan dan pidato de-ngan bait-bait puitis penuh hikmah yang bisa dibaca dalam Nahj al-Balaghah. Para ulama dari kalangan tabiin (generasi pascasahabat) juga diketahui banyak mengajarkan hikmah dan substansi Islam dengan ung-kapan-ungkapan puitis. Hasan al-Bashri (w. 728 M), Srid ibn al-Musayyib (w. 715 M), Abū Hazim al-A'raj (w. 781 M), dan lainnya, dikenal piawai dengan ungkapan-ungkapan puitis dalam pengajaran Islam sehingga mudah mengetuk sanubari yang mendengarkannya. Tradisi ini diteruskan lagi oleh para ulama generasi berikutnya (tabi' al-tabi'in), seperti Sufyan al-Tsawri (w. 778 M), Malik ibn Anas (w.795 M), Al-Fudayl ibn 'lyäd (w. 803 M), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 820 M), dan lain-lain.
Tulisan bersambung:
- Lebaran Sastra: Menggincui Madrasah dengan Puisi
- Sastra dan Pesantren
- Lebaran Sastra: Upaya Memanggil Tradisi untuk Kembali
Para ulama ini tidak sekadar mengajarkan Islam untuk mudah dipahami, tapi juga mengajarkan dengan bahasa yang menyentuh sanubari. Jika mereka meng-ajarkan larangan tertentu, seperti untuk tidak sombong, disampaikan dengan ungkapan lebih menyentuh hati yang mendengarnya. Seperti ungkapan Sufyan al-Tsawri berikut: Jika engkau bisa menjadi orang yang tidak dikenal, lakukanlah. Apa kerugian bagimu tak dipuji manusia, jika engkau dipuji oleh Allah yang Maha Segalanya?). Atau ungkapan Hasan al-Bashri berikut: Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah sebagian dari dirimu). kumpulan hari. Setiap kali hari berlalu, berlalu pula
Mengajarkan Islam dengan ujaran yang nyaman didengarkan atau tulisan yang bernada ketika dibaca adalah cara para ulama untuk memelihara tradisi su-sastra yang diilhami oleh gaya bahasa Al-Qur'an. Ini juga perintah Al-Qur'an (16:125) dalam mengajarkan Islam, yakni dengan hikmah, dengan nasihat (ungkapan) yang baik (indah), dan bantahan yang tidak melahirkan amarah.
Di Indonesia, tradisi itu pun tak lekang oleh jarak, tak redup oleh waktu. Karya-karya para ulama klasik Nusantara, seperti Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M), Mir'at al-Mu'minin oleh Syamsuddin al-Sumatrani (w. 1630 M), Tarjuman al-Mustafid oleh Abd al-Ra'uf al-Sinkili (w. 1693 M), Zubdat al-Asrár oleh Syaikh Yusuf al-Maqassari (w. 1699 M), Bustan al-Katibin, Tuhfat al-Nafis, Muqaddimah Fi Intizam dan Gurindam Duabelas karya Syaikh Raja Ali Haji (w. 1873 M), semua ditulis dengan ungkapan-ungkapan puitis yang padat metafora, rima, dan, tentu saja, hikmah.
Karya-karya tersebut menjadi bagian penting dari khazanah karya sastra dalam Islam. Penggunaan gaya tutur puitis dalam tulisan mereka menjadi ciri penting bagaimana puisi dan tradisi panjang pengajaran Islam memang harmonis sedari awal. Secara personal saya selalu kagum dengan cara para ulama menuliskan ungkapan-ungkapan yang terkesan lirih, penuh metafor, tanpa harus kehilangan esensi dari ajaran Islam. Terang bahwa puisi bukan hal yang mesti "dicurigai," melainkan seyogianya diberikan ruang edukatif dan transformatif demi mengawal dinamika sosial kehidupan, sekaligus kehambaan tiap diri. Sebagaimana disinyalir Raja Ali Haji (2000: vii), "Disyairkan supaya menambahi peringatan, supaya tetap menambah taghrib pada orang yang membacanya, supaya lapang daripada lelah dan jemu membacanya. Lil taghrib dan menjadi dasrul kalam."
Tradisi susastra para ulama tentu saja di luar fakta bahwa sebagian dari mereka juga dikenal sebagai pujangga pada zamannya. Hamzah Fansuri (w. 1590 M) dan Raja Ali Haji (w. 1873 M) adalah ulama-ulama sufi, guru dari ulama terkenal lainnya, yakni Syamsuddin al-Sumatrani yang dikenal sebagai penyair Melayu pertama (Aljunied, 2019: Al-Attas, 1970). Beberapa karyanya dalam bentuk prosa seperti Sharab al-'ashiqin, Asrar al-'arifin, Kitab al-Muntahi, ataupun puisi-puisinya, kental dengan ajaran tasawuf dan hikmah. Apa yang unik dari sosok Hamzah Fansuri adalah gaya individualitas sebagai suatu gaya baru dalam tradisi sastra Melayu (Teeuw, 1994). Dalam bentuk puisi, karyanya tidak lepas dari nuansa sufistik yang menunjukkan jati dirinya sebagai ulama:
Laut Kulzum terlalu dalam.
ombakuya muhit pada sekalian alam
banyaklah di sana rusak dan karum,
perbaiki na'am, siang dan malam.
Dalam syair tersebut, Hamzah Fansuri menampilkan frasa "laut Kulzum sebagai metafora untuk lautan hakikat (kebenaran tertinggi). Secara pribadi saya juga suka penggunaan istilah muhit, diambil dari bahasa Arab, yang berarti meliputi. Istilah muhit merupakan salah satu nama dari sekian banyak nama Tuhan yang baik. Istilah ini menggambarkan bahwa ombak (perlambang cobaan spiritual dari lautan hakikat) itu menggetarkan dan meliputi seluruh alam semesta, atau tak seorang pun yang luput dari pengaruhnya. Dalam perjalanan mengarungi lautan hakikat (Kulzum) tersebut, banyak orang tergelincir, tersesat, salah arah, dan tenggelam. Karena itu, orang perlu memperbaki iman, ketakwaan, dan ketaatan pada Tuhan selama hidup. Istilah "na'am." merujuk pada totalitas kepasrahan dan ketulusan penghambaan tiap diri sepanjang waktu, siang, serta malam. Terlebih tiap diri ini diciptakan Allah SWT ha-nya untuk menyembah kepada-Nya. Tak ada pilihan (QS. 51: 56).
Demikian pula yang diutarakan amat puitis oleh Raja Ali Haji (w. 1873 M), dalam Gurindam Duabelas (2000: 2-16), "Barang siapa tiada memegang agama/sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama//barang siapa mengenal yang empat/maka yaitulah orang yang makrifat//barang siapa mengenal Allah/suruh dan tegahnya tiada ia menyalah//barang siapa mengenal diri/maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari//... jika hendak mengenal orang yang berilmu/bertanya dan belajar tiadalah jemu//jika hendak mengenal orang yang berakal/di dalam dunia mengambil bekal//...cahari olehmu akan sahabat/yang boleh dijadikan obat//cahari olehmu akan guru/yang boleh tahukan tiap seteru//cahari olehmu akan kawan/pilih segala orang yang setiawan//..barang siapa khianat akan dirinya/apalagi kepada lainnya//..jika orang muda kuat berguru/dengan syaitan jadi berseteru//...kasihkan orang yang berilmu/tanda rahmat atas dirimu//hormat akan orang yang pandai/tanda mengenal kasa dan cindai//...ingatkan dirinya mati/itulah asal berbuat bakti"
Tulisan bersambung:
- Lebaran Sastra: Menggincui Madrasah dengan Puisi
- Sastra dan Pesantren
- Lebaran Sastra: Upaya Memanggil Tradisi untuk Kembali
Pilihan